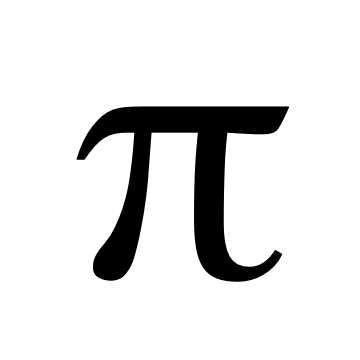.
.
.
di sisa-sisa derai hujan kata-kata
dikayuhnya langkah ke dalam kabut
menerawang cakrawala dalam benaknya
sendiri...
jejak-jejak hujan tinggal rintik (seperti rintih) menabuh riak-riak lirih pada genang-genangan air di atas aspal dan beton jalan raya, memantulkan wajah langit senja tanpa warna selain kelabu pekat yang sejenak lagi kan habis pula ditelan kelam malam-malam tanpa bintang-bintang yang menyisakan muram rembulan desember dalam kesepiannya sendiri di hamparan kegelapan menyaksikan hingar-bingar pesta terompet dan kembang api yang pada akhirnya selalu kan hanya menyisakan kepulan asap beraroma mesiu sebelum hilang dilahap kesunyian yang sama-sama menyesakkan
di sisa-sisa derai hujan kata-kata
dikayuhnya langkah ke dalam kabut
menyelami samudra dalam hatinya
sendiri...
segala yang hilang ditelan waktu akankah berakhir sebagai kubangan kenangan di relung-relung ingatan yang begitu mudahnya tersapu banjir bandang dalam terpaan badai informasi yang ditiupkan gelagat cuaca tak menentu dari wacana-wacana dunia maya yang tak lagi dapat terbaca sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh bermakna sedikitpun yang pada akhirnya hanya menyisakan sampah-sampah slogan-slogan dangkal fabrikasi instan propaganda tanpa alamat yang kelak terbuang di selokan-selokan umpatan mampet, di sungai-sungai pikiran keruh, sebelum berakhir di dasar lautan kata-kata mati, kuburan aksara (yang akhirnya musnah*) tanpa pusara
di sisa-sisa derai hujan kata-kata
dikayuhnya langkah ke dalam kabut
merenungi semesta dalam dirinya
sendiri...
mencari sesuatu yang mungkin tertingal pada jejak-jejak laju peradaban yang sudah telanjur melesat melampaui masa depan, atau yang mungkin tercecer di antara sisa-sisa ampas pembangunan yang telanjur mengabaikan manusia dalam prosesnya, atau terselip di sela-sela tumpukan reruntuhan masa silam yang telanjur dikuburkan tanpa upacara penghormatan, terhimpit ruang-ruang sempit di dinding-dinding mewah kota-kota yang begitu angkuh menginjak-injak kesederhanan desa-desa
tenggelam dalam sepi
menghanyutkannya ke dalam mimpi
esok hari ia terbangun
mendapati kenyataan yang sama
kecuali dirinya
sendiri...
Jogja, 30-31 Desember 2019
*'aksara' konon berasal dari bahasa sansekerta. a: tidak, dan khsara: termusnahkan
Tentang Kenyataan Irasional - Sebuah Pengakuan (?)
untuk memahami semua ini
kau harus bersedia menerima
bahwa ada kenyataan
yang mengandung kebenaran
dalam dirinya sendiri,
tak peduli betapa irasionalnya3
kenyataan itu bagimu.
demikian pula …
*
Sebenarnya aku tak ingat lagi bagaimana mulanya perasaan itu ada. Namun demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sering menghantuiku, pertanyaan-pertanyaan kurang penting yang sesungguhnya juga berasal dari diriku sendiri, aku jadi merasa perlu—jika tidak ingin berkata harus—mengarang-ngarang sebuah cerita sehingga terciptalah ranah kemungkinan bagi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengada.
Dengan kata lain, akan sah-sah sajalah kiranya apabila semua ini kau anggap sekadar mengada-ada. Namun kupikir, begitulah kita semua sebenarnya dalam memaknai kehidupan kita masing-masing: dengan mengada-adakan makna. Sebab makna tidak mungkin ada kecuali diada-adakan. Paling tidak selama kita masih belum cukup berani meyakininya.
Maka begitulah, dan meskipun sebagian peristiwa yang kujadikan sebagai kerangka untuk membangun cerita yang kumaksud itu –mungkin saja—memang adalah fakta, namun kurasa banyak juga di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang sesungguhnya cuma –dan tidak lebih dari sekadar—fiksi belaka. Jika ditanyai perihal mana yang lebih dominan, aku sendiri pun rasanya tidak akan dapat memberi jawaban yang memuaskan. Tetapi bila terpaksa, akan kukatakan bahwa unsur fiksilah yang lebih banyak ketimbang faktanya.
Di satu sisi, ini dapat menjadi petunjuk bahwa bahkan diriku sendiri pun ternyata tidak terlalu percaya pada cerita yang sudah repot-repot kususun itu. Meski demikian, setidak-tidaknya, dengan adanya cerita itu, maka ada yang dapat kuceritakan untuk mengisi lubang-lubang menganga yang biasanya ditinggalkan oleh pertayaan-pertanyaan yang selalu saja datang di saat-saat tak terduga itu. Biarpun belum akan cukup untuk memenuhinya, tetapi kurasa itu masih lebih mending daripada membiarkannya tetap kosong sama sekali.
Di sisi lain, kurasa aku masih dapat sedikit menangkal ketidakpercayaanku sendiri itu dengan membawa-bawa sepenggal kredo Seno Gumira Ajidarma 1 ke dalam argumen yang melatarbelakangi ceritaku, bahwa fakta atau fiksi itu sekadar bentuk saja, sekadar “cara” menyampaikan, sedangkan kebenaran yang terkandung di dalamnya–kalau memang ada—akan tetap ada sebagai kebenaran, yang pada akhirnya tidak lagi dapat dipungkiri.
Meskipun kebenaran itu sendiri mungkin saja memang “mustahil” diketahui, serta dapat pula ditutup-tutupi maupun disangkal, namun resonansi getarannya akan tetap dapat dirasakan. Hingga pada akhirnya kebenaran itu sendirilah yang akan mematahkan setiap sangkalan dan menyeruak menyibak tabir yang menutup-nutupinya, untuk hadir di hadapan kita tanpa bisa lagi dihindari sama sekali.
Demikianlah, cerita itu, meski belum sepenuhnya dapat menghapus semua tanda tanya yang tiada surut-surutnya menggali lubang-lubang kekosongan dalam diriku, paling tidak masih cukup manjur untuk meredakan gejala-gejalanya. Seperti yang kurasa telah dimaksudkan oleh ‘helai-helai kertas’ dalam sajak Seremoni Umbu Landu Paranggi 2:
dengan mata pena kugali-gali seluruh diriku
dengan helai-helai kertas kututup nganga luka-lukaku
kupancing udara di dalam dengan angin di tanganku
begitulah, kutulis nyawaMu senyawa dengan nyawaku
Dan begitulah pula, kuharap, aku bisa menuliskan nyawamu senyawa dengan nyawaku.
*
Cerita itu:
Apa yang kelak menjelma perasaan itu mungkin sudah terlanjur jatuh sebagai benih ketika pertama kali aku berjumpa denganmu. Waktu itu aku hanyalah sabana tandus, di suatu musim kemarau, yang sedang tak percaya bahwa akan tiba suatu saat di mana musim berganti dan hujan pun akan turun.
Kubiarkan angin berlalu tanpa peduli pada apa yang mungkin dibawanya pergi dan apa yang mungkin ditinggalkannya. Seperti orang-orang yang senantiasa datang dan pergi dalam hidup ini. Seperti jika aku berdiri di tepi jalanan kota, menanti hadirnya celah yang bisa kuseberangi, semetara wajah-wajah terus berkelabatan di atas kendaraan yang berlalu-lalang. Atau sebaliknya, seperti jika aku berkendara menyusuri jalanan kota yang ramai, melewati berbagai tempat, melewati banyak orang, tanpa pernah sempat benar-benar meyaksikan semua itu.
Perjumpaan denganmu, dan yang kemudian lambat laun menjadi perkenalan itu, bagiku hanyalah angin yang sehari-hari berhembus melintasi sabana. Tetapi yang mungkin tak kusadari adalah apa yang ditinggalkannya, terselip di antara rumpun-rumpun ilalang yang sekarat, atau terjatuh ke dalam celah retakan tanah keringku. Menetap di situ, lama. Cukup lama –mungkin sangat lama—dan seharusnya bisa saja kemudian hancur dan terurai menjadi debu tanpa pernah menjadi perlu kuketahui adanya. Kecuali ternyata tidak.
Angin rupanya tak selalu berhembus dari selatan membawa serbuk-serbuk debu dari gurun di pedalaman sebuah benua tandus. Suatu ketika ia akan datang dari utara membawa serbuk-serbuk gerimis dan benih-benih hujan dari samudera luas yang menyimpan berbagai kemungkinan –termasuk kemungkinan-kemungkinan yang seolah-olah tak mungkin bagi kita. Kemungkinan-kemungkinan yang gagal diperkirakan sebagai kemungkinan.
Seketika hujan pun turun membasahi rumput-rumput sekarat, lalu air mengalir mengisi celah-celah tanah retak, pada suatu malam yang tanpa rembulan, dan kutemukan diriku berada pada sebuah sudut di petak ruang persegi dengan pikiran buntu dan mulut terkunci menatap sudut lain di seberang ruangan itu, menyaksikan warna-warni ajaib dalam sepasang bola mata yang sesugguhnya sudah teralu sering kulihat di hari-hari dan malam-malam yang lain namun belum pernah jadi seajaib itu.
“setiap tetes hujan mengandung benih pelangi …”
*
Sayangnya aku mungkin masih terlalu lugu tenggelam dalam skeptisisme naifku sendiri ketika menanggapi keajaiban tersebut. Meskipun sejak malam itu selalu kujumpai lagi keajaiban itu hampir setiap hari bila menatap mata itu, namun aku akan selalu meletakkannya dalam bingkai tanda tanya, di balik kaca yang tercipta dari bias-bias asumsi yang seakan-akan paling jernih untuk menilai kenyataan sebagai sesuatu yang objektif—dan dari sudut pandang sempit yang terlalu mengagung-agungkan objektivitas rasional sebagai satu-satunya cara untuk menilai kebenaran pada sebuah kenyataan.
Betapapun keajaiban itu senantiasa hadir setiap kali kutatap mata itu, tak pernah kubiarkan diriku menerimanya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Akan selalu kutempatkan perasaan itu dalam bingkai tanda tanya di balik kaca bias-bias asumsi naifku, dan kugantungkan pada dinding ruang sempit tempat segala sesuatu yang kucurigai terpatri dalam benakku.
Baru kusadari di kemudian hari, betapa bodohnya aku mengira bahwa kenyataan hanyalah segala sesuatu yang objektif dan rasional belaka. Menyangka bahwa segala sesuatu yang benar-benar nyata hanyalah yang dapat ditampung oleh kapasitas ruang berpikir dalam benakku yang –ternyata—amat sangat sempit ini. Sedangkan kehidupan dengan segala fenomenanya akan selalu terlalu besar untuk dijejalkan ke dalam ruang di kepala kita.
Kukira aku akan dapat menentukan jarak antara dua titik sudut berhadapan pada sebuah persegi (jarak yang telah melahirkan warna-warni ajaib ketika aku menatap mata itu pada suatu malam yang tanpa rembulan) dalam angka rasional sampai digit terakhir sebelum mengakuinya sebagai kenyataan. Kukira aku akan dapat menentukan panjang lintasan jalan yang kutempuh ketika mengitari suatu titik (perasaan yang telah melahirkan warna-warni ajaib itu) dengan tetap menjaga jarak rasional yang sama terhadap titik tersebut sepanjang perjalananku—sehingga lintasan tersebut menjadi sebuah lingkaran sempurna—sebagai sebuah bilangan yang rasional.
Pada akhirnya aku menyadari bahwa selama ini, sejak malam yang tanpa rembulan itu, aku telah melakukan sesuatu yang begitu sia-sia. Menderetkan angka demi angka di belakang tanda koma, berharap akan tiba pada angka terakhir untuk meyakinkan diriku bahwa jarak antara dua titik sudut itu, panjang keliling lingkaran itu, adalah bilangan rasional.
Sebuah usaha yang ternyata tidak akan pernah berakhir sebab jarak dan panjang lintasan itu memang irasional adanya. Dan betapapun irasionalnya, kedua hal itu tetap adalah kenyataan yang tak terbantahkan adanya sebagai kebenaran dalam dirinya sendiri. Sedangkan setiap usaha menutup-nutupi dan menyangkalnya hanya akan melahirkan kekacauan dalam usaha manusia memahami dunia ini.
Mungkin demikianlah aku telah menciptakan kekacauan dalam diriku sendiri. Bahwa perasaan yang selama ini kejejalkan ke dalam bingkai tanda tanya itu sejak semula adalah kenyataan yang mengandung kebenaran dalam dirinya sendiri, betapapun irasionalnya.
Jogjakarta, 15-16 Desember 2019
Catatan-catatan:
- Seno Gumira Ajidarma, dalam Ketika Jurnalise Dibungkam Sastra Harus Bicara pernah menulis: “Bagi saya, dalam bentuk fakta maupun fiksi, kebenaran adalah kebenaran—yang getarannya bisa dirasakan setiap orang.” (sumber: Trilogi Insiden oleh Seno Gumira Ajidarma terbitan Bentang Pustaka tahun: lupa).
- Sajak berjudul Seremoni karya Umbu Landu Paranggi yang pernah dimuat dalam Bali Post tahun 1978 (sumber: Blog Kepada Puisi, tautan: http://kepadapuisi.blogspot.com/2015/04/sepilihan-puisi-umbu-landu-paranggi.html, diakses pada: 16 Desember 2019).
- Kata ‘rasional’ maupun ‘irasional’ dalam tulisan ini sesungguhnya adalah campur aduk istilah Matematika dan Bahasa, yang apabila ditelusuri dalam kamus ternyata mengandung arti yang –meskipun menurut penulis sangat mirip bahkan mungkin sesungguhnya sama, namun tetap saja menurut kamus—berbeda satu sama lain. Dalam konteks Bahasa, kata ‘rasional’ adalah kata sifat yang secara umum berarti ‘masuk akal’ atau ‘logis’ (adapun lawan katanya yaitu ‘irasional’ berarti ‘tidak masuk akal’ atau ‘tidak logis’). Sedangkan dalam konteks Matematika, kata ‘rasional’ yang dimaksud terkait dengan pengertian tentang jenis bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan (rasio) dua bilangan bulat (integer), sementara ‘irasional’ terkait dengan pengertian tentang jenis bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat (untuk lebih memahami, silakan menelusuri tautan berikut saja: https://www.mathsisfun.com/irrational-numbers.html). Adapun bilangan irasional yang dimaksud dalam konteks Matematika tidaklah berarti bahwa bilangan tersebut ‘tidak masuk akal’ atau ‘tidak logis’, meskipun kalau coba direnung-renungkan lebih jauh bisa saja kita kemudian merasa kesulitan memahaminya dengan akal. Dari situlah penulis kemudian merasakan bahwa mungkin saja istilah dalam kedua konteks tersebut sesungguhnya dapat bermakna sama—atau setidaknya mirip. Atau mungkin juga si penulis sendiri saja yang memang kurang “jenius”.
kupu-kupu di bawah hujan
...
kupu-kupu berteduh di bawah hujan
kata-kata beterbangan di dalam pikiran
seperti tak tahu hendak ke mana
kita pun tak tahu harus berkata apa
selain berharap menunggu reda
sampai habis udara di dada
menahan rintik demi rintik
melahap detik demi detik
sampai basah
sampai menyerah
menelan getir kenyataan
menelan semua pertanyaan
tanpa ada jawaban
tanpa kesimpulan
Teluk Dalam, 27 November 2019
// pagi waktu gerimis
kupu-kupu berteduh di bawah hujan
kata-kata beterbangan di dalam pikiran
seperti tak tahu hendak ke mana
kita pun tak tahu harus berkata apa
selain berharap menunggu reda
sampai habis udara di dada
menahan rintik demi rintik
melahap detik demi detik
sampai basah
sampai menyerah
menelan getir kenyataan
menelan semua pertanyaan
tanpa ada jawaban
tanpa kesimpulan
Teluk Dalam, 27 November 2019
// pagi waktu gerimis
ha*
kita
pengembara
tersesat di belantara kata-kata
terombang-ambing di samudera makna
menatap cakrawala wacana
tanpa tahu menuju ke mana
namun setidak-tidaknya
kita masih bisa tertawa
ha
ha
*wacana
Teluk Dalam, 27 November 2019
pengembara
tersesat di belantara kata-kata
terombang-ambing di samudera makna
menatap cakrawala wacana
tanpa tahu menuju ke mana
namun setidak-tidaknya
kita masih bisa tertawa
ha
ha
*wacana
Teluk Dalam, 27 November 2019
kuburan sepi
...
dan di balik tumpukan bangkai kata-kata
terkuburlah sepi yang tak pernah mati
meski diberondong peluru-peluru bising
dari moncong-moncong peradaban
industri konsumsi informasi
yang tak mengenal batas.
meski ditikam beribu-ribu
belati berlumur racun
dari tangan-tangan biadab
para konglomerat serakah.
meski dihujani panah-panah api
kebencian yang terlepas dari jari-jari
manis janji-janji palsu para politisi.
meski terus dikebiri
dipenggal dan dimutilasi
dengan definisi-definisi sakral
kemudian diasingkan
dalam lembaran-lembaran kitab suci
yang dikunci dalam lemari-lemari besi
di bawah pengawasan kepala-kepala raksasa
para cerdikiawan berhati sempit.
sepi tak bisa dibungkam.
sepi tak dapat dibunuh dengan cara apapun,
meski masih mungkin bisa kau pungkiri
sampai nanti kau lelah sendiri
lalu sadar mesti kembali
ke dalam sepi
rumahmu yang sejati
dan dari kuburan-kuburan sepi
kata-kata mati, huruf-huruf mati
kelak akan tumbuh entah apa
yang baru kan bermakna
setelah habis kau sesapi
segala-galanya yang tak berarti
begitulah konon penciptaan puisi*
*(setidak-tidaknya yang satu ini)
Teluk Dalam, 25 November 2019
dan di balik tumpukan bangkai kata-kata
terkuburlah sepi yang tak pernah mati
meski diberondong peluru-peluru bising
dari moncong-moncong peradaban
industri konsumsi informasi
yang tak mengenal batas.
meski ditikam beribu-ribu
belati berlumur racun
dari tangan-tangan biadab
para konglomerat serakah.
meski dihujani panah-panah api
kebencian yang terlepas dari jari-jari
manis janji-janji palsu para politisi.
meski terus dikebiri
dipenggal dan dimutilasi
dengan definisi-definisi sakral
kemudian diasingkan
dalam lembaran-lembaran kitab suci
yang dikunci dalam lemari-lemari besi
di bawah pengawasan kepala-kepala raksasa
para cerdikiawan berhati sempit.
sepi tak bisa dibungkam.
sepi tak dapat dibunuh dengan cara apapun,
meski masih mungkin bisa kau pungkiri
sampai nanti kau lelah sendiri
lalu sadar mesti kembali
ke dalam sepi
rumahmu yang sejati
dan dari kuburan-kuburan sepi
kata-kata mati, huruf-huruf mati
kelak akan tumbuh entah apa
yang baru kan bermakna
setelah habis kau sesapi
segala-galanya yang tak berarti
begitulah konon penciptaan puisi*
*(setidak-tidaknya yang satu ini)
Teluk Dalam, 25 November 2019
perjalanan
.
aku
berjalan
dari kata ke kata
meniti huruf demi huruf
tertatih-tatih, terbata-bata
mengeja pertanda
mencari arti
mengerti
berarti
sampai mati.
Teluk Dalam, 21-22 November 2019
aku
berjalan
dari kata ke kata
meniti huruf demi huruf
tertatih-tatih, terbata-bata
mengeja pertanda
mencari arti
mengerti
berarti
sampai mati.
Teluk Dalam, 21-22 November 2019
gelandangan di belantara sepi
.
Aku bertanya pada bunyi jangkrik yang menebar benih-benih gerimis di atas tanah yang gersang sedang pohon-pohon berdahan telanjang tetap saja membisu di tengah kepungan jilat api yang pelan-pelan menjalar di atas bangkai-bangkai ilalang.
Aku bertanya pada luka di tubuh tanpa nyawa meski tetap bernama yang seperti kata-kata tanpa makna yang terserak di sepanjang jalan raya antara duka dan derita.
Di manakah kita dapat bertemu apabila kata-kata tak pernah ada sementara dunia ini begini sepi?
Namun kata-kata pun semakin sepi tanpa arti lagi.
Dan perlahan-lahan ia jadi rapuh.
Tinggal menunggu runtuh.
Lalu kita
gelandangan di belantara sepi,
di sabana huruf-huruf mati.
Teluk Dalam, 21 November 2019 // malam
Pada Suatu Perjalanan
kutelusuri baris-baris puisi
menuju ruang dalam diri
kata-kata berguguran
dari pohon sebatang kara
rindu diterbangkan angin
menyeberangi sabana
buih-buih kenangan
pecah di udara
di ujung gelombang
terbentur batu-batu karang
di tanah jejak-jejak kata
huruf-huruf mati berserakan
menjadi satu dengan debu
terbang bersama rindu
melintasi padang ilalang
menebas batas cakrawala
lalu hilang
ditelan bias serpihan kenangan
Bintan, September 2019
menuju ruang dalam diri
kata-kata berguguran
dari pohon sebatang kara
rindu diterbangkan angin
menyeberangi sabana
buih-buih kenangan
pecah di udara
di ujung gelombang
terbentur batu-batu karang
di tanah jejak-jejak kata
huruf-huruf mati berserakan
menjadi satu dengan debu
terbang bersama rindu
melintasi padang ilalang
menebas batas cakrawala
lalu hilang
ditelan bias serpihan kenangan
Bintan, September 2019
ingin ku..
/* d
di benakmu
benang-benang kusut
di hatimu
gumpalan kabut
di matamu
hari-hari kian redup
...
ingin kubentang jalan panjang
dari ujung ke ujung cakrawala
supaya dapat kau urai benakmu
di atasnya, sembari kau kenyam langkah
di hadapan mega-mega senjakala
ingin kuhampar padang luas
supaya angin tak betah berdiam diri
lalu datang mengajak bermain
rerumpun ilalang dan daun-daun
dan kabut kan sirna dengan sendirinya
ingin kutatap matamu lekat-lekat
melepas kata-kata yang lama kudekap
dalam bilik sunyi di sepi hatiku
biar terbang sebebas burung-burung
cahaya yang membawa pesan
tentang yang begitu dalam terpendam
~Bintan, Agustus 2019
di benakmu
benang-benang kusut
di hatimu
gumpalan kabut
di matamu
hari-hari kian redup
...
ingin kubentang jalan panjang
dari ujung ke ujung cakrawala
supaya dapat kau urai benakmu
di atasnya, sembari kau kenyam langkah
di hadapan mega-mega senjakala
ingin kuhampar padang luas
supaya angin tak betah berdiam diri
lalu datang mengajak bermain
rerumpun ilalang dan daun-daun
dan kabut kan sirna dengan sendirinya
ingin kutatap matamu lekat-lekat
melepas kata-kata yang lama kudekap
dalam bilik sunyi di sepi hatiku
biar terbang sebebas burung-burung
cahaya yang membawa pesan
tentang yang begitu dalam terpendam
~Bintan, Agustus 2019
dalam hujan
/* d
"Setiap tetes hujan mengandung benih pelangi"
Begitu katamu dulu
"Namun hanya di matamu pelangi bisa tumbuh"
Aku lalu tersipu malu
"Tetapi cuma aku yang bisa melihatnya"
Matamu menembus rinai hujan
Kutanya mengapa begitu,
"Karena cinta adalah cahaya," jawabmu
...
Sejak saat itu
aku menunggu
jawaban atas sebuah pertanyaan
yang terselip di antara rinai hujan
Apakah kamu
mencintaiku?
Sebab hujan terlanjur reda
membawa serta semua kata-kata
Sedang kita pun mesti tergesa-gesa
kembali berlari mengejar dunia
Bintan, September 2019
"Setiap tetes hujan mengandung benih pelangi"
Begitu katamu dulu
"Namun hanya di matamu pelangi bisa tumbuh"
Aku lalu tersipu malu
"Tetapi cuma aku yang bisa melihatnya"
Matamu menembus rinai hujan
Kutanya mengapa begitu,
"Karena cinta adalah cahaya," jawabmu
...
Sejak saat itu
aku menunggu
jawaban atas sebuah pertanyaan
yang terselip di antara rinai hujan
Apakah kamu
mencintaiku?
Sebab hujan terlanjur reda
membawa serta semua kata-kata
Sedang kita pun mesti tergesa-gesa
kembali berlari mengejar dunia
Bintan, September 2019
Lamunan Sesa(a)t
Kudapati diri tersesat di kota itu,
maka duduklah aku di sebuah bangku
di bawah bayang-bayang pohon Trembesi
di trotoar berdebu. Kuamat-amati
waktu berlalu.
Seorang kakek tua bermata gelap
berambut putih panjang
bertubuh ringkih
terbungkus lembaran kain
lusuh tebal berdebu
telah duduk di sudut simpang jalan itu
sejak waktu pertama kali
hadir di hadapan kehidupan.
Konon, manusia
terlahir dari perkawinan
antara kehidupan dan kematian
di atas altar keabadian, namun waktu
menggali jebakan jurang fana
yang memisahkan keduanya, lalu
meninggalkan manusia
yatim piatu di dunia.
Waktu
memenggal-menggal keabadian, lalu
memenjarakan masing-masing penggalan
dalam siklus lingkaran-lingkaran perulangan,
disegel dengan simbol-simbol
dua belas bilangan, dan
dijaga bergantian oleh siang dan malam.
Lalu bertahta Ia di singgahsananya
yang senantiasa berputar, mengawasi
segalanya dari pusat alam semesta.
Kakek tua yang duduk
di sudut simpang jalan itu,
menurut kabar cicit burung
yang konon pernah mendengar
desas-desus yang kadang kala
diperbincangkan angin dan dedaunan
ketika mereka bercengkerama
di dahan-dahan pepohonan,
adalah satu-satunya manusia
yang berhasil lolos dari jebakan
waktu.
Ia kan terus duduk di situ,
memaku pandangnya
pada jam yang terpatri
di atas menara
batu pualam yang menjulang
di tengah persimpangan jalan
tanpa pernah berkedip sedikitpun.
Mungkin ia sedang mencari celah
di mana waktu akan lengah
lalu menyelinap di sela-sela
pergantian siang dan malam
untuk membebaskan keabadian
lalu menyatukan kembali kehidupan
dan kematian.
Tetapi aku lalu tersadar dari lamunan.
Bintan, September 2019
maka duduklah aku di sebuah bangku
di bawah bayang-bayang pohon Trembesi
di trotoar berdebu. Kuamat-amati
waktu berlalu.
Seorang kakek tua bermata gelap
berambut putih panjang
bertubuh ringkih
terbungkus lembaran kain
lusuh tebal berdebu
telah duduk di sudut simpang jalan itu
sejak waktu pertama kali
hadir di hadapan kehidupan.
Konon, manusia
terlahir dari perkawinan
antara kehidupan dan kematian
di atas altar keabadian, namun waktu
menggali jebakan jurang fana
yang memisahkan keduanya, lalu
meninggalkan manusia
yatim piatu di dunia.
Waktu
memenggal-menggal keabadian, lalu
memenjarakan masing-masing penggalan
dalam siklus lingkaran-lingkaran perulangan,
disegel dengan simbol-simbol
dua belas bilangan, dan
dijaga bergantian oleh siang dan malam.
Lalu bertahta Ia di singgahsananya
yang senantiasa berputar, mengawasi
segalanya dari pusat alam semesta.
Kakek tua yang duduk
di sudut simpang jalan itu,
menurut kabar cicit burung
yang konon pernah mendengar
desas-desus yang kadang kala
diperbincangkan angin dan dedaunan
ketika mereka bercengkerama
di dahan-dahan pepohonan,
adalah satu-satunya manusia
yang berhasil lolos dari jebakan
waktu.
Ia kan terus duduk di situ,
memaku pandangnya
pada jam yang terpatri
di atas menara
batu pualam yang menjulang
di tengah persimpangan jalan
tanpa pernah berkedip sedikitpun.
Mungkin ia sedang mencari celah
di mana waktu akan lengah
lalu menyelinap di sela-sela
pergantian siang dan malam
untuk membebaskan keabadian
lalu menyatukan kembali kehidupan
dan kematian.
Tetapi aku lalu tersadar dari lamunan.
Bintan, September 2019
Malam-malam Gelap
...
malam-malam gelap menyelinap
menyembunyikan mimpi-mimpi
di antara bintang-bintang
di balik sinar rembulan
di lubuk samudera keheningan
malam-malam gelap
biarlah kudekap
dalam lelap tidurku
malam-malam gelap
di manakah mimpi-mimpiku?
malam-malam gelap
biarlah mengendap
di dasar gelasku
malam-malam gelap
biarlah menguap
di hembus nafasku
selamat pagi
malam-malam gelap
di manakah mimpi-mimpiku?
malam-malam gelap kusekap
dalam bilik pengap
di bawah cahaya lampu merkuri
di hadapan moncong senapan
berisi peluru seribu satu pertanyaan
di manakah mimpi-mimpiku?
~
betapa malam-malam gelap
memang tak pernah bicara
kecuali dalam isyarat bisu
bernama kesunyian
~Bintan, Agustus 2019
malam-malam gelap menyelinap
menyembunyikan mimpi-mimpi
di antara bintang-bintang
di balik sinar rembulan
di lubuk samudera keheningan
malam-malam gelap
biarlah kudekap
dalam lelap tidurku
malam-malam gelap
di manakah mimpi-mimpiku?
malam-malam gelap
biarlah mengendap
di dasar gelasku
malam-malam gelap
biarlah menguap
di hembus nafasku
selamat pagi
malam-malam gelap
di manakah mimpi-mimpiku?
malam-malam gelap kusekap
dalam bilik pengap
di bawah cahaya lampu merkuri
di hadapan moncong senapan
berisi peluru seribu satu pertanyaan
di manakah mimpi-mimpiku?
~
betapa malam-malam gelap
memang tak pernah bicara
kecuali dalam isyarat bisu
bernama kesunyian
~Bintan, Agustus 2019
tiada lagi
/* d
Kau bilang jarak menghamparkan ruang
dan aku menjelma hampa
dalam kabut yang mengambang
di atas aliran sungai air mata
Kau bilang jeda merentangkan waktu
dan aku menunggu sia-sia
di tepi jurang masa lalu
menangisi abu kenangan yang tersisa
Katamu sepi menghadirkan diri
dan kuselami samudera tanpa nama
mencari-cari wajahku di tengah ramai
meraba-raba bayangku di antara ada dan tiada
Katamu sunyi menjernihkan bunyi
dan aku tenggelam dalam pusaran gelombang maya
menjadi serpihan-serpihan puisi
yang mati ditelan riuh kata-kata
katamu tiada lagi...
kita...
~Bintan, 26-28 Agustus 2019
Kau bilang jarak menghamparkan ruang
dan aku menjelma hampa
dalam kabut yang mengambang
di atas aliran sungai air mata
Kau bilang jeda merentangkan waktu
dan aku menunggu sia-sia
di tepi jurang masa lalu
menangisi abu kenangan yang tersisa
Katamu sepi menghadirkan diri
dan kuselami samudera tanpa nama
mencari-cari wajahku di tengah ramai
meraba-raba bayangku di antara ada dan tiada
Katamu sunyi menjernihkan bunyi
dan aku tenggelam dalam pusaran gelombang maya
menjadi serpihan-serpihan puisi
yang mati ditelan riuh kata-kata
katamu tiada lagi...
kita...
~Bintan, 26-28 Agustus 2019
November
Kupandang cakrawala di balik kaca jendela. Bayang-bayang gedung-gedung tinggi berbaris menutupi garis horison. Awan kelabu yang seperti bercampur dengan asap pekat masih setia menyembunyikan birunya langit.
Tumpukan berkas terbuka di layar komputer di hadapanku. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Dan di ujung hembusan nafas itu, aku tenggelam dalam lamunan.
Di bawah sana, di dalam salah satu toko kelontong di pinggir sebuah ruas jalan yang macet, seorang pemilik toko mungkin baru saja menyobek selembar kertas berangka 31 dari tumpukan kertas berangka yang tergantung di dinding tokonya, meninggalkan kertas berangka 1 terpampang jelas di dinding itu.
November telah tiba. Wajar saja orang-orang mulai mendambakan hujan. Lagipula mungkin mereka juga sudah cukup muak menghirup asap dari knalpot kendaraan, cerobong pabrik, atau dari lahan-lahan yang terbakar yang belakangan menyesaki udara negeri ini.
Diam-diam aku pun turut mendambakan hujan, meski karena suatu alasan yang agak berbeda. Mungkin lebih tepat kukatakan bahwa aku mendambakan langit biru. Langit yang masih tersembunyi di balik gumpalan asap tebal dan awan kelabu yang terus menerus menggantung di cakrawala itu.
Kulirik kalender segitiga di pojok mejaku yang ternyata masih menampilkan halaman bulan Oktober. Kubalik halaman kalender itu ke bulan November. Selama beberapa saat, kupandangi halaman bulan November itu. Kutelusuri deretan angka-angkanya dari angka terakhir hingga kutemukan letak salah satu angka yang lalu kutandai dengan semacam stabilo di dalam kepalaku. Kemudian kutelusuri kembali barisan angka itu sampai ke angka 1 sebelum kemudian kulemparkan pandanganku jauh menembus kaca jendela, bahkan melampaui cakrawala.
Kubayangkan sehelai daun jatuh ke tanah di suatu tempat di bumi ini. Mungkin oleh sebab tiupan angin yang berhembus dari laut, atau mungkin cuma karena tarikan gravitasi bumi. Namun di balik itu semua, kurasa waktulah yang sesungguhnya paling bertanggung jawab.
Waktu.
Tiba-tiba aku membayangkan bahwa mungkin terdapat hubungan erat di antara peristiwa gugurnya daun dari ranting pohon itu dengan tersobeknya lembaran kertas berangka pada dinding sebuah toko kelontong di pinggir ruas jalan yang macet itu.
Aku bukanlah seorang yang cerdas dan tidak pula berdaya ingat tajam, namun kadang kala aku bisa tiba-tiba teringat pada satu dua hal yang dulu pernah kupelajari di bangku sekolah. Peristiwa seperti itu biasanya terjadi tanpa sengaja. Kadang itu membuatku kesal sendiri sebab kebanyakan hal yang berusaha kuingat biasanya malah tidak dapat kuingat sama sekali, sementara hal semacam itu, yang seringkali tidak begitu penting sebenarnya, malah dapat kuingat begitu saja tanpa usaha sama sekali. Seolah-olah ingatan memang memiliki kehendaknya sendiri dan bisa seenaknya datang dan pergi begitu saja.
Aku teringat dalam pelajaran Bahasa Indonesia terdapat istilah 'homonim' yang mengacu pada dua kata yang mirip atau bahkan identik yang sesungguhnya mengandung arti yang sama sekali berbeda. Dan di antara kata-kata tersebut adalah 'tanggal'.
Sayangnya tidak ada cara bagiku untuk meneliti asal-usul kata itu, untuk mencari tahu apakah memang terdapat benang merah di antara keduanya atau tidak. Namun kurasa tiada yang berhak melarangku untuk meyakini bahwa kata-kata itu memang sesungguhnya sangat erat berkaitan satu sama lain.
Maka aku seringkali membayangkan waktu menjelma pohon raksasa dengan banyak dahan dan cabang yang diam-diam menanggalkan daunnya satu demi satu, seperti setiap unit ukuran waktu yang hilang dalam pergeseran ujung jarum jam dinding, atau seperti setiap lembaran kertas berangka yang tersobek dari kalender di dinding ketika hari, bulan, dan tahun berganti.
Apakah kau juga berpikiran demikian?
Aku mungkin akan menanyakan hal itu kepadamu nanti, kalau kebetulan kita berkesempatan mengobrol tentang hal-hal random lagi.
...
Mendung seperti betah sekali menggantung di atas kota ini. Tiada setitik pun celah. Cakrawala sempurna dalam kelabu. Apakah hujan akan turun hari ini?
Aku bertanya pada waktu, yang tentu saja selalu hanya bisa menyuruh untuk menunggu.
Entah berapa banyak sudah daun yang jatuh ke tanah sejak kumulai lamunanku hari itu. Namun aku ternyata masih betah berlama-lama menatap langit kelabu di balik kaca jendela itu. Seperti menunggu, namun tidak terlalu berharap. Tumpukan berkas yang terbuka di layar komputer di hadapanku pun harus rela menunggu lebih lama lagi.
Aku mulai mengingat-ingat beberapa kata yang pernah kubaca dalam beberapa puisi yang pernah kau tuliskan dalam kumpulan kertas bekas yang kau jadikan buku catatan untuk mencatat apa saja. Kata-kata yang berkaitan dengan waktu. Aku ingat kau banyak membicarakan waktu dalam tulisan-tulisanmu.
//
Mungkin kita sesungguhnya hanyalah sebersit rindu yang membentang tipis di antara masa lalu yang hampir terlupakan dan masa depan yang seakan tak mungkin [terwujudkan], menunggu waktu kembali menyusut menjadi satu titik dari mana segalanya pernah bermula dan ke mana segalanya kan berakhir.
//
Kurasa aku tak kan mungkin dapat melupakan hal-hal tertentu dari masa laluku. Namun seandainya memang ingatan punya kebebasannya sendiri, dapat menetap atau pergi sesukanya tanpa kita dapat mencegah, mungkin saja suatu saat aku akan melupakan semua itu. Mungkin aku akan melupakanmu juga, tak peduli sekeras apa aku berusaha menjaga ingatan itu.
Bangku semen yang lembab dan berlumut. Tiang-tiang lampu yang melengkung seperti pakis muda. Pohon Trembesi dan Sawo Kecik. Lele dan tempe goreng tepung. Es teh.Tanda tangan palsu di lembar presensi. Debu-debu vulkanik. Genangan-genangan air sehabis hujan.
//
Titik-titik hujan seperti ingatan yang terpecah dan berhamburan jatuh dari langit.
//
Aku ingat kau pernah mengatakan sesuatu kepadaku di sela-sela rintik hujan dan lalu-lalang kendaraan. Aku ingat kau sempat terdiam begitu lama sebelum tiba-tiba mengucapkannya. Aku ingat aku jadi tak mampu berkata-kata setelah mendengarnya. Namun aku tak dapat mengingat lagi apa yang waktu itu kau katakan. Apakah itu sebuah pernyataan, ataukah pertanyaan? Yang kuingat, setelah itu malam jadi begitu panjang dan aku tak dapat tidur. Sepanjang malam yang kupikirkan cuma kata-katamu itu. Kata-kata yang tak lagi dapat kuingat.
Kata-kata.
Betapa aneh rasanya kita membicarakan kata-kata dengan kata-kata. Namun mungkin itu sekadar hal lumrah yang baru sempat terpikirkan olehku saja. Seperti halnya memikirkan pikiran kita sendiri. Atau mengobrol dengan diri sendiri.
Katamu kata-kata pernah menghantarkanmu menuju pintu gerbang sebuah dunia yang begitu sepi dan sunyi. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku memahami sepenuhnya apa yang kau maksud, namun aku rasa aku mungkin mengerti. Meskipun tetap saja, bagiku kau selalu penuh misteri. Seperti gunung berselimut kabut. Seperti langit tertutupi mendung.
Aku termenung. "Langit tertutupi mendung."
Mungkinkah karena itu aku jadi menanti-nanti hujan?
//Dalam derai hujan mengurai mendung.//
Aku mulai melihat ada kata-kata yang terbang berputar-putar dalam benakku, seperti serangga-serangga musim penghujan yang kerap beterbangan di sekitar lampu jalanan. Mungkin itu hanya sekadar pikiran random saja, sebab kata-kata itu tidak menjelma kalimat yang masuk akal. Tetapi semakin lama kuperhatikan, seakan ada pesan tertentu yang terkandung di dalamnya, yang mungkin hanya belum dapat kurumuskan saja. Maka kubiarkan kata-kata itu terus terbang berkeliaran dalam benakku, dan aku menjadi seperti anak kecil yang berdiri tengadah di bawah lampu jalanan, menyaksikan serangga-serangga beterbangan ke sana ke mari mengitari bola lampu.
Puisi-puisimu adalah hujan yang kunantikan. Setiap tetesnya adalah kata yang kuharap kan mengurai mendung dan membasuh udara. Pada akhirnya semoga kan dapat kujumpai langit biru; segala yang kau simpan dalam benakmu, dan yang kau pendam dalam hatimu.
Kilatan petir tiba-tiba menyambar membelah cakrawala dan menggetarkan kaca jendela. Mendung semakin pekat, namun apakah hujan akan benar-benar turun hari ini?
"Yah, please jangan hujan dulu dong, aku ga bawa payung nih!"
Seseorang yang duduk dua meja dari mejaku bergumam. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan sedang bersiap-siap pulang.
Kuhela nafas panjang lalu kembali menatap tumpukan berkas di layar komputer di hadapanku. Mungkin sebaiknya segera kuselesaikan saja pekerjaan yang telah menunggu sejak tadi ini.
[]
November 2019
Tumpukan berkas terbuka di layar komputer di hadapanku. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan. Dan di ujung hembusan nafas itu, aku tenggelam dalam lamunan.
Di bawah sana, di dalam salah satu toko kelontong di pinggir sebuah ruas jalan yang macet, seorang pemilik toko mungkin baru saja menyobek selembar kertas berangka 31 dari tumpukan kertas berangka yang tergantung di dinding tokonya, meninggalkan kertas berangka 1 terpampang jelas di dinding itu.
November telah tiba. Wajar saja orang-orang mulai mendambakan hujan. Lagipula mungkin mereka juga sudah cukup muak menghirup asap dari knalpot kendaraan, cerobong pabrik, atau dari lahan-lahan yang terbakar yang belakangan menyesaki udara negeri ini.
Diam-diam aku pun turut mendambakan hujan, meski karena suatu alasan yang agak berbeda. Mungkin lebih tepat kukatakan bahwa aku mendambakan langit biru. Langit yang masih tersembunyi di balik gumpalan asap tebal dan awan kelabu yang terus menerus menggantung di cakrawala itu.
Kulirik kalender segitiga di pojok mejaku yang ternyata masih menampilkan halaman bulan Oktober. Kubalik halaman kalender itu ke bulan November. Selama beberapa saat, kupandangi halaman bulan November itu. Kutelusuri deretan angka-angkanya dari angka terakhir hingga kutemukan letak salah satu angka yang lalu kutandai dengan semacam stabilo di dalam kepalaku. Kemudian kutelusuri kembali barisan angka itu sampai ke angka 1 sebelum kemudian kulemparkan pandanganku jauh menembus kaca jendela, bahkan melampaui cakrawala.
Kubayangkan sehelai daun jatuh ke tanah di suatu tempat di bumi ini. Mungkin oleh sebab tiupan angin yang berhembus dari laut, atau mungkin cuma karena tarikan gravitasi bumi. Namun di balik itu semua, kurasa waktulah yang sesungguhnya paling bertanggung jawab.
Waktu.
Tiba-tiba aku membayangkan bahwa mungkin terdapat hubungan erat di antara peristiwa gugurnya daun dari ranting pohon itu dengan tersobeknya lembaran kertas berangka pada dinding sebuah toko kelontong di pinggir ruas jalan yang macet itu.
Aku bukanlah seorang yang cerdas dan tidak pula berdaya ingat tajam, namun kadang kala aku bisa tiba-tiba teringat pada satu dua hal yang dulu pernah kupelajari di bangku sekolah. Peristiwa seperti itu biasanya terjadi tanpa sengaja. Kadang itu membuatku kesal sendiri sebab kebanyakan hal yang berusaha kuingat biasanya malah tidak dapat kuingat sama sekali, sementara hal semacam itu, yang seringkali tidak begitu penting sebenarnya, malah dapat kuingat begitu saja tanpa usaha sama sekali. Seolah-olah ingatan memang memiliki kehendaknya sendiri dan bisa seenaknya datang dan pergi begitu saja.
Aku teringat dalam pelajaran Bahasa Indonesia terdapat istilah 'homonim' yang mengacu pada dua kata yang mirip atau bahkan identik yang sesungguhnya mengandung arti yang sama sekali berbeda. Dan di antara kata-kata tersebut adalah 'tanggal'.
Sayangnya tidak ada cara bagiku untuk meneliti asal-usul kata itu, untuk mencari tahu apakah memang terdapat benang merah di antara keduanya atau tidak. Namun kurasa tiada yang berhak melarangku untuk meyakini bahwa kata-kata itu memang sesungguhnya sangat erat berkaitan satu sama lain.
Maka aku seringkali membayangkan waktu menjelma pohon raksasa dengan banyak dahan dan cabang yang diam-diam menanggalkan daunnya satu demi satu, seperti setiap unit ukuran waktu yang hilang dalam pergeseran ujung jarum jam dinding, atau seperti setiap lembaran kertas berangka yang tersobek dari kalender di dinding ketika hari, bulan, dan tahun berganti.
Apakah kau juga berpikiran demikian?
Aku mungkin akan menanyakan hal itu kepadamu nanti, kalau kebetulan kita berkesempatan mengobrol tentang hal-hal random lagi.
...
Mendung seperti betah sekali menggantung di atas kota ini. Tiada setitik pun celah. Cakrawala sempurna dalam kelabu. Apakah hujan akan turun hari ini?
Aku bertanya pada waktu, yang tentu saja selalu hanya bisa menyuruh untuk menunggu.
Entah berapa banyak sudah daun yang jatuh ke tanah sejak kumulai lamunanku hari itu. Namun aku ternyata masih betah berlama-lama menatap langit kelabu di balik kaca jendela itu. Seperti menunggu, namun tidak terlalu berharap. Tumpukan berkas yang terbuka di layar komputer di hadapanku pun harus rela menunggu lebih lama lagi.
Aku mulai mengingat-ingat beberapa kata yang pernah kubaca dalam beberapa puisi yang pernah kau tuliskan dalam kumpulan kertas bekas yang kau jadikan buku catatan untuk mencatat apa saja. Kata-kata yang berkaitan dengan waktu. Aku ingat kau banyak membicarakan waktu dalam tulisan-tulisanmu.
//
Mungkin kita sesungguhnya hanyalah sebersit rindu yang membentang tipis di antara masa lalu yang hampir terlupakan dan masa depan yang seakan tak mungkin [terwujudkan], menunggu waktu kembali menyusut menjadi satu titik dari mana segalanya pernah bermula dan ke mana segalanya kan berakhir.
//
Kurasa aku tak kan mungkin dapat melupakan hal-hal tertentu dari masa laluku. Namun seandainya memang ingatan punya kebebasannya sendiri, dapat menetap atau pergi sesukanya tanpa kita dapat mencegah, mungkin saja suatu saat aku akan melupakan semua itu. Mungkin aku akan melupakanmu juga, tak peduli sekeras apa aku berusaha menjaga ingatan itu.
Bangku semen yang lembab dan berlumut. Tiang-tiang lampu yang melengkung seperti pakis muda. Pohon Trembesi dan Sawo Kecik. Lele dan tempe goreng tepung. Es teh.Tanda tangan palsu di lembar presensi. Debu-debu vulkanik. Genangan-genangan air sehabis hujan.
//
Titik-titik hujan seperti ingatan yang terpecah dan berhamburan jatuh dari langit.
//
Aku ingat kau pernah mengatakan sesuatu kepadaku di sela-sela rintik hujan dan lalu-lalang kendaraan. Aku ingat kau sempat terdiam begitu lama sebelum tiba-tiba mengucapkannya. Aku ingat aku jadi tak mampu berkata-kata setelah mendengarnya. Namun aku tak dapat mengingat lagi apa yang waktu itu kau katakan. Apakah itu sebuah pernyataan, ataukah pertanyaan? Yang kuingat, setelah itu malam jadi begitu panjang dan aku tak dapat tidur. Sepanjang malam yang kupikirkan cuma kata-katamu itu. Kata-kata yang tak lagi dapat kuingat.
Kata-kata.
Betapa aneh rasanya kita membicarakan kata-kata dengan kata-kata. Namun mungkin itu sekadar hal lumrah yang baru sempat terpikirkan olehku saja. Seperti halnya memikirkan pikiran kita sendiri. Atau mengobrol dengan diri sendiri.
Katamu kata-kata pernah menghantarkanmu menuju pintu gerbang sebuah dunia yang begitu sepi dan sunyi. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku memahami sepenuhnya apa yang kau maksud, namun aku rasa aku mungkin mengerti. Meskipun tetap saja, bagiku kau selalu penuh misteri. Seperti gunung berselimut kabut. Seperti langit tertutupi mendung.
Aku termenung. "Langit tertutupi mendung."
Mungkinkah karena itu aku jadi menanti-nanti hujan?
//Dalam derai hujan mengurai mendung.//
Aku mulai melihat ada kata-kata yang terbang berputar-putar dalam benakku, seperti serangga-serangga musim penghujan yang kerap beterbangan di sekitar lampu jalanan. Mungkin itu hanya sekadar pikiran random saja, sebab kata-kata itu tidak menjelma kalimat yang masuk akal. Tetapi semakin lama kuperhatikan, seakan ada pesan tertentu yang terkandung di dalamnya, yang mungkin hanya belum dapat kurumuskan saja. Maka kubiarkan kata-kata itu terus terbang berkeliaran dalam benakku, dan aku menjadi seperti anak kecil yang berdiri tengadah di bawah lampu jalanan, menyaksikan serangga-serangga beterbangan ke sana ke mari mengitari bola lampu.
Puisi-puisimu adalah hujan yang kunantikan. Setiap tetesnya adalah kata yang kuharap kan mengurai mendung dan membasuh udara. Pada akhirnya semoga kan dapat kujumpai langit biru; segala yang kau simpan dalam benakmu, dan yang kau pendam dalam hatimu.
Kilatan petir tiba-tiba menyambar membelah cakrawala dan menggetarkan kaca jendela. Mendung semakin pekat, namun apakah hujan akan benar-benar turun hari ini?
"Yah, please jangan hujan dulu dong, aku ga bawa payung nih!"
Seseorang yang duduk dua meja dari mejaku bergumam. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan sedang bersiap-siap pulang.
Kuhela nafas panjang lalu kembali menatap tumpukan berkas di layar komputer di hadapanku. Mungkin sebaiknya segera kuselesaikan saja pekerjaan yang telah menunggu sejak tadi ini.
[]
November 2019
Sia-Sia
Malam larut dalam gelasmu
mengendap-endapkan gelap
ke dasar terdalam lubuk hatimu
Pahit kau reguk
dalam sukma
Kabut asap di cakrawala
membaur biaskan cahaya
di ruang hampa dalam benakmu
Sesak kau hirup
dalam dada
Daun-daun kering dalam gulungan kertas
di antara jemari dan sela bibirmu
Jilat api di tangkub telapak tanganmu
Bara menyala di ujung lidahmu
Kata-kata
tak kunjung tiba
Sepi kau hela
Sunyi kau hembuskan
Yang tersisa
sia-sia
Teluk Dalam, 5-6 November 2019
//
mengenang semesta
dan malam-malam yang "sia-sia"
mengendap-endapkan gelap
ke dasar terdalam lubuk hatimu
Pahit kau reguk
dalam sukma
Kabut asap di cakrawala
membaur biaskan cahaya
di ruang hampa dalam benakmu
Sesak kau hirup
dalam dada
Daun-daun kering dalam gulungan kertas
di antara jemari dan sela bibirmu
Jilat api di tangkub telapak tanganmu
Bara menyala di ujung lidahmu
Kata-kata
tak kunjung tiba
Sepi kau hela
Sunyi kau hembuskan
Yang tersisa
sia-sia
Teluk Dalam, 5-6 November 2019
//
mengenang semesta
dan malam-malam yang "sia-sia"
Telur
Kau sedang dalam perjalanan pulang ketika kematian menjemputmu.
Sebuah kecelakaan mobil. Tidak terlalu parah, namun tetap fatal. Kau mati meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Sebuah kematian yang tanpa rasa sakit. Para petugas medis darurat sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkan nyawamu, namun pada akhirnya tetap tak berhasil. Tubuhmu benar-benar hancur, jadi memang lebih baik kau mati, percayalah.
Dan ketika itulah kau bertemu denganku.
"A... apa yang telah terjadi?" kau bertanya. "Di mana ini?"
"Kau sudah mati," kataku terus terang. Tiada gunanya bertele-tele.
"Tadi ada truk dan... dan... truk itu selip..."
"Yap," kataku.
"A... aku sudah mati?"
"Yap. Tapi jangan khawatir. Semua orang juga akan mati," kataku.
Kau memandangi sekeliling. Tiada sesuatu apapun. Cuma kau dan aku. "Tempat apa ini?" Kau bertanya. "Inikah akhirat?"
"Kurang lebih," kataku.
"Apakah kau adalah tuhan?" Kau bertanya.
"Yap," jawabku. "Aku adalah Tuhan."
"Anak-anakku... istriku," katamu.
"Ada apa dengan mereka?"
"Apakah mereka akan baik-baik saja?"
"Itulah yang kuharapkan," kataku. "Kau baru saja mati dan hal pertama yang kau khawatirkan adalah keluargamu. Bagus."
Kau menatapku heran. Bagimu, aku sama sekali tidak seperti Tuhan. Aku terlihat seperti manusia biasa saja. Semacam figur orang tua yang aneh. Lebih seperti seorang guru di sekolah dibanding Tuhan.
"Jangan khawatir," kataku. "Mereka akan baik-baik saja. Anak-anakmu akan mengenangmu sebagai sosok yang sempurna dalam segala hal. Mereka belum sempat melihat hal-hal buruk tentangmu. Istrimu akan menangisimu, namun diam-diam ia merasa lega. Sebenarnya rumah tanggamu sedang menuju kehancuran. Supaya kau tenang saja, istrimu akan merasa sangat bersalah atas perasaan leganya."
"Oh," katamu. "Lantas bagaimana sekarang? Apakah aku akan masuk surga atau neraka atau apa?"
"Tidak," kataku. "Kau akan bereinkarnasi."
"Oh," katamu. "Jadi ajaran Hindulah yang benar."
"Semua ajaran agama itu benar dalam caranya masing-masing," kataku. "Mari berjalan bersamaku."
Kau mengikutiku berjalan menyusuri kehampaan. "Ke mana kita?"
"Tidak ke mana-mana," kataku. "Hanya saja, rasanya lebih enak kalau mengobrol sambil jalan-jalan."
"Jadi, apa gunanya, kalau begitu?" Kau bertanya. "Kalau aku terlahir kembali, aku tidak akan mengingat apa-apa, kan? Menjadi bayi lagi. Jadi semua yang pernah kualami dan kulakukan dalam kehidupan ini tidak akan ada artinya."
"Tidak juga," kataku. "Kau menyimpan di dalam dirimu semua pengetahuan dan pengalaman dari seluruh kehidupan yang telah kau lalui. Kau hanya belum dapat mengingatnya sekarang."
Kuhentikan langkah dan kupegang bahumu. "Ruhmu memiliki kemampuan yang jauh lebih luar biasa daripada yang mampu kau bayangkan. Pikiran manusia hanya dapat menampung sebagian sangat kecil dari dirinya yang sesungguhnya. Seperti menyentuhkan ujung jari pada segelas air untuk mengecek apakah air itu panas atau dingin. Kau taruh sebagian kecil dirimu ke dalam wadah wadagmu, dan ketika kau menariknya kembali, kau mendapatkan semua pengalaman yang diperolehnya.
"Kau baru saja menempati tubuh seorang manusia selama paling tidak 48 tahun, jadi kau belum sepenuhnya bersatu kembali dengan seluruh kesadaranmu. Kalau kau sudah berada di sini cukup lama, kau akan mulai mengingat segalanya. Namun tidak ada gunanya menunggu selama itu setiap kali kau akan berpindah kehidupan."
"Lalu sudah berapa kali aku bereinkarnasi?"
"Berkali-kali. Sangat banyak sekali. Sudah begitu banyak kehidupan berbeda yang kau lalui." Kataku. "Kali ini kau akan menjadi seorang gadis petani di Negeri Cina pada tahun 540 M."
"Tunggu dulu." Kau terkejut. "Kau mengirimku ke masa lalu?"
"Secara teknis, iya. Waktu, kau tahu, hanya ada di semestamu. Berbeda dengan di tempat asalku."
"Dari mana asalmu?" Katamu.
"Tentu saja," aku menjelaskan "dari suatu tempat. Suatu tempat yang lain. Dan ada banyak yang lain sepertiku. Aku mengerti kau mungkin ingin tahu seperti apa tempat itu, namun kau tak akan mengerti meskipun kujelaskan."
"Oh," katamu, sedikit kecewa. "Tapi tunggu dulu. Kalau aku bereinkarnasi ke masa yang berbeda, aku bisa saja bertemu dengan diriku yang lain secara kebetulan kan."
"Tentu. Hal seperti itu sering terjadi. Dan karena masing-masing kehidupan itu hanya bisa menyadari hidupnya masing-masing, kau tidak akan menyadari hal itu."
"Lalu apa artinya semua itu?"
"Serius?" Tanyaku. "Kau bertanya padaku tentang makna kehidupan? Tidakkah itu agak menyindir?"
"Itu pertanyaan yang cukup masuk akal, kan," kau bersikeras.
Kutatap matamu. "Makna kehidupan, alasan mengapa aku menciptakan alam semesta ini adalah supaya kau menjadi lebih dewasa, lebih cerdas, dan lebih bijaksana."
"Cuma aku? Bagaimana dengan orang-orang lainnya?"
"Tidak ada yang lain," kataku. Di alam semesta ini hanya ada kau dan aku."
Kau menatapku lekat-lekat. "Tapi semua orang di bumi..."
"Semuanya adalah kau. Inkarnasi yang berbeda-beda dari dirimu."
"Tunggu. Aku adalah semua orang!?"
"Sekarang kau mulai mengerti," kataku sambil memberi tepukan selamat di punggungmu.
"Aku adalah semua manusia yang pernah hidup?"
"Atau yang akan pernah hidup, benar."
"Aku Abraham Lincoln?"
"Dan kau juga John Wilkes Booth," aku menambahkan.
"Aku Hitler?" Katamu, dengan nada menyesal.
"Dan kau adalah jutaan orang yang dibunuhnya."
"Aku Yesus?"
"Dan kau adalah murid-muridnya."
Kau terdiam membisu.
"Setiap kali kau menyakiti seseorang," kataku, "kau menyakiti dirimu sendiri. Setiap kebaikan yang kau lakukan, kau lakukan kepada dirimu sendiri. Setiap momen bahagia maupun sedih yang pernah dialami manusia telah, dan akan, kau alami."
Kau berpikir lama.
"Mengapa?" Kau bertanya. "Mengapa kau lakukan semua ini?"
"Karena suatu saat nanti, kau akan menjadi sepertiku. Karena itulah dirimu yang sesungguhnya. Kau adalah salah satu di antara aku. Kau anakku."
"Wow," katamu tak percaya. "Maksudmu aku adalah tuhan?"
"Tidak. Belum. Kau masih janin. Kau masih sedang tumbuh. Setelah kau menjalani kehidupan seluruh manusia di semua waktu, barulah kau akan terlahir."
"Jadi seluruh alam semesta," katamu, "adalah..."
"Sebutir telur." Jawabku. "Sekarang, sudah saatnya kau melanjutkan ke kehidupanmu yang berikutnya."
Dan kukirim kau ke jalanmu. []
_________
Bintan, 1-2 September 2019
Diterjemahkan dari The Egg karya Andy Weir (naskah asli: http://www.galactanet.com/oneoff/theegg_mod.html)
KRIM
Kuceritakan kepada kawan mudaku tentang sebuah peristiwa yang terjadi ketika aku berusia delapan belas tahun. Entah mengapa aku menceritakannya. Itu terjadi begitu saja selagi kami mengobrol. Betapa pun semua itu terjadi sudah lama sekali. Semacam sejarah usang yang bahkan hingga saat ini tak pernah dapat kutarik sebuah kesimpulan apapun darinya.
“Waktu itu aku sudah tamat SMA, tetapi belum kuliah,” aku menjelaskan. “Bisa dikatakan aku seperti seorang ronin akademik, seorang pelajar yang gagal di ujian penerimaan universitas dan sedang menunggu kesempatan untuk mencoba lagi. Segala sesuatu mengenai nasibku terasa belum begitu jelas,” lanjutku, “namun semua itu tidak terlalu kuhiraukan. Aku yakin aku bisa diterima di universitas swasta yang lumayan bagus kalau mau. Tetapi orang tuaku bersikeras agar aku mencoba mendaftar di universitas negeri, jadi kuikuti ujian seleksi, meskipun aku tahu bahwa aku akan gagal. Dan, tentu saja, aku pun gagal. Ujian nasional penerimaan universitas waktu itu memiliki soal matematika wajib, sedangkan aku sama sekali tidak tertarik dengan kalkulus. Kuhabiskan tahun berikutnya dengan membiarkan waktu berlalu begitu saja, seolah-olah aku memang sengaja menciptakan alibi. Alih-alih mengambil kursus bimbingan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, aku malah asik menghabiskan waktu di perpustakaan lokal, menenggelamkan diri dalam novel-novel tebal. Orang tuaku pasti mengira aku belajar di sana. Namun begitulah hidup, bukan. Aku lebih menikmati membaca semua karya Balzac daripada bersusah payah memahami prinsip-prinsip kalkulus.”
Di awal Oktober tahun itu, aku menerima sebuah undangan untuk menghadiri pertunjukan piano dari seorang perempuan yang setingkat di bawahku ketika sekolah dulu dan pernah belajar piano pada guru yang sama denganku. Pernah sekali kami berdua bersama-sama memainkan karya pendek Mozart yang memang diciptakan untuk dimainkan dengan empat tangan. Namun ketika aku beranjak memasuki usia enam belas tahun, aku berhenti belajar piano, dan tidak lagi pernah bertemu dengannya sejak itu. Jadi aku pun heran mengapa ia mengirimiku undangan ini. Apakah ia tertarik kepadaku? Tidak mungkin. Dia memang menarik, meskipun bukan tipeku dalam hal penampilan; dia selalu mengenakan pakaian bagus dan sekolah di sekolah swasta mahal khusus perempuan. Sama sekali bukan tipe gadis yang akan tertarik pada laki-laki yang biasa-biasa saja sepertiku.
Ketika kami memainkan karya Mozart itu bersama-sama, dia sering memberiku tatapan tak menyenangkan bila aku menekan nada yang salah. Dia adalah pemain piano yang lebih baik daripada aku, dan aku sering mudah gugup, jadi ketika kami berdua duduk berdampingan dan memainkan piano bersama-sama aku sering melakukan kesalahan. Beberapa kali pula sikuku membentur sikunya. Itu sebenarnya bukanlah karya yang sulit untuk dimainkan, dan lagi pula aku mendapatkan bagian yang lebih mudah. Tiap kali aku mengacau, dia selalu menunjukkan ekspresi masa gitu aja ga bisa!? kepadaku. Dan dia akan berdecak—tidak keras namun cukup keras hingga dapat terdengar olehku. Aku bahkan masih ingat suara decakan itu sampai sekarang. Suara itu mungkin pula telah turut andil dalam keputusanku untuk berhenti belajar piano.
Hubunganku dengannya cuma sebatas itu, pernah belajar piano di sekolah musik yang sama. Kami saling menyapa kalau kebetulan ketemu, namun sama sekali tidak pernah, seingatku, kami berbagi hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi menerima undangan untuk menghadiri pertunjukan pianonya (bukan pertunjukan solo melainkan berkelompok dengan dua orang pemain piano lainnya) secara tiba-tiba tentu saja membuatku heran –dan bahkan tercengang. Namun satu hal yang melimpah padaku tahun itu adalah waktu, maka kukirimkan kartu pos berisi pesan balasan yang mengatakan bahwa aku akan datang. Salah satu alasan aku melakukan itu adalah karena aku penasaran ingin mengetahui apa kiranya alasan yang tersembunyi di balik undangan itu—kalau memang ada. Kalau tidak, mengapa pula dia mengirimiku undangan itu setelah sekian lama? Mungkin dia telah menjadi pemain piano yang jago dan bermaksud menunjukkan itu padaku. Atau mungkin ada alasan pribadi yang hendak dia utarakan kepadaku. Dengan kata lain, waktu itu aku benar-benar penasaran dan sedang berusaha memuaskan rasa penasaran tersebut.
Gedung pertunjukan itu berada di daerah puncak salah satu pegunungan di Kobe. Kuambil jalur kereta Hankyu terdekat, kemudian naik bus melalui jalanan berliku yang menanjak. Aku turun di perhentian bus yang berada paling dekat dengan puncak, dan setelah berjalan kaki sebentar aku pun tiba di gedung pertunjukan yang lumayan besar, yang dimiliki dan dikelola oleh seorang konglomerat kaya raya. Sama sekali aku tak tahu sebelumnya bahwa di tempat seperti itu, di puncak gunung, di sebuah lingkungan pemukiman kelas atas yang sepi, terdapat sebuah gedung pertunjukan. Tentu saja, ada banyak sekali hal di dunia ini yang belum kuketahui waktu itu.
Untuk menunjukkan apresiasiku atas undangan yang kuterima aku merasa perlu membawa sesuatu, maka aku telah membeli sebuket bunga yang kupikir akan cocok untuk kubawa di sebuah toko bunga dekat stasiun. Tepat setelahnya bus itu kemudian tiba dan aku langsung melompat naik. Itu adalah suatu Minggu sore yang dingin. Langit tersembunyi di balik awan kelabu yang tebal, sedemikian tebalnya hingga seakan-akan hujan yang dingin dapat turun setiap saat. Namun tidak ada angin sama sekali. Aku mengenakan sweater polos tipis di bawah jaket bermotif herringbone abu-abu dengan sentuhan warna biru, dan sebuah tas kanvas terselempang di bahuku. Jaket itu masih baru, sedangkan tas itu sudah tua dan usang. Dan di tanganku sebuket bunga-bunga merah dalam bungkusan plastik transparan. Ketika kumasuki bus dengan penampilan mencolok itu, para penumpang lain terus-terusan memandangiku. Atau mungkin itu cuma perasaanku saja. Pipiku rasanya bersemu merah. Dulu, mudah sekali wajahku memerah seperti itu. Dan akan butuh waktu lama untuk hilang.
“Demi apakah aku berada di sini?” aku bertanya pada diri sendiri, sembari mengambil tempat duduk, mencoba menutupi merah wajahku dengan kedua tangan. Aku tidak benar-benar ingin menemui gadis ini, atau ingin menyaksikan pertunjukan pianonya, jadi mengapa aku rela sampai membuang-buang uang hanya untuk membeli sebuket bunga dan menempuh perjalanan sejauh ini menuju puncak pegunungan pada suatu Minggu sore yang muram di bulan November? Pasti ada sesuatu yang tak beres denganku ketika kumasukkan kartu pos balasan itu ke dalam kotak surat.
Semakin tinggi bus itu mendaki, semakin berkurang penumpangnya, dan ketika akhirnya sampai di perhentian yang kutuju hanya tinggal aku dan si supir saja di dalamnya. Aku turun dari bus dan berjalan menyusuri jalanan yang mendaki landai sesuai petunjuk yang tertera di undangan. Setiap kali aku berjalan di jalanan yang menikung, aku bisa melihat pelabuhan untuk sesaat sebelum kemudian hilang lagi dari ranah pandangku. Langit terlihat pucat seakan-akan dilapisi timah. Di pelabuhan terlihat beberapa crane raksasa, seperti semacam antena milik sebuah mahluk aneh yang sedang merangkak keluar dari dalam lautan.
Rumah-rumah yang ada di daerah puncak pegunungan itu besar-besar dan megah, dengan dinding-dinding batu yang kokoh, pintu-pintu gerbang yang mewah, dan garasi yang luas. Jajaran bunga-bunga kertas terpangkas dengan rapi. Kudengar suara seperti anjing menggonggong entah di mana. Tiga kali gonggongan keras, kemudian, seolah-olah ada yang telah membentaknya, gonggongan itu tiba-tiba berhenti, dan yang tersisa tinggal keheningan yang mendalam.
Ketika kutelusuri peta petunjuk sederhana pada undangan itu, sebersit firasat tidak menyenangkan tiba-tiba menghantuiku. Ada yang tidak beres. Pertama-tama, jalanan itu terlalu sepi. Sejak turun dari bus tidak satupun orang kutemui di jalanan. Memang ada dua mobil yang lewat, namun keduanya mengarah turun, tidak naik. Seandainya memang ada pertunjukan di sini, seharusnya aku akan menemui banyak orang. Tapi daerah itu begitu sepi dan sunyi, seolah-olah awan tebal di atas sana telah menyedot semua suara yang mungkin ada.
Apakah aku telah keliru?
Kukeluarkan lagi undangan itu dari kantong jaketku untuk mengecek kembali. Mungkin saja aku telah salah membacanya. Maka kubaca kembali dengan hati-hati, namun tidak kutemukan ada yang salah. Nama jalan, tempat perhentian bus, dan tanggal serta waktunya semua benar. Kutarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian kulanjutkan langkahku. Satu-satunya yang bisa kulakukan cuma menemukan gedung pertunjukan yang dimaksud dan menyaksikannya secara langsung.
Ketika akhirnya kutemukan gedung itu, kudapati pintu gerbang besinya yang besar ternyata tertutup rapat dan terkunci. Ada rantai tebal melilitinya, dan gembok kokoh yang berat menguncinya. Tidak ada orang sama sekali. Melalui sela-sela pintu gerbang kulihat halaman parkir dan tidak kutemukan satupun mobil terparkir di situ. Rumput-rumput liar tumbuh dari sela-sela paving blok, dan halaman parkir itu seperti telah cukup lama tak digunakan lagi. Tetapi papan nama besar yang terpampang di pintu masuknya menunjukkan bahwa memang inilah gedung pertunjukan yang kucari.
Kutekan tombol interkom di sebelah pintu masuk itu namun tidak ada yang menjawab. Kutunggu beberapa saat, lalu kutekan lagi tombol itu, namun tetap tidak ada jawaban. Kulihat jam tanganku. Pertunjukan piano itu seharusnya akan dimulai lima belas menit lagi. Namun tidak ada tanda-tanda pintu gerbang itu akan dibuka. Catnya sudah terkelupas di beberapa titik, dan karat mulai menggerogotinya. Karena tak tahu harus melakukan apa, maka kutekan sekali lagi tombol interkom itu, agak lama, namun hasilnya sama saja –hening.
Tak tahu harus melakukan apa lagi, kuhabiskan sekitar sepuluh menit bersandar pada pintu gerbang itu. Mungkin saja seseorang akan muncul tak lama lagi. Namun tidak seorang pun yang datang. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda pergerakan baik di dalam maupun di luar gerbang itu. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung, tidak pula gonggongan anjing. Seperti sebelumnya, awan tebal tanpa celah menggantung di atas sana.
Akhirnya aku pun menyerah –mau bagamana lagi?—dan dengan berat hati aku berjalan turun kembali ke arah perhentian bus, tanpa memahami sama sekali apa yang sedang berlangsung. Satu hal yang jelas adalah bahwa tidak ada pertunjukan piano atau acara apapun yang akan berlangsung di sini hari ini. Aku tak punya pilihan lain kecuali pulang ke rumah, dengan sebuket bunga-bunga merah di tangan. Ingin kubuang di tempat sampah dekat stasiun, tapi sayang–-harganya cukup mahal hanya untuk dibuang begitu saja.
*
Belum terlalu jauh aku berjalan menuruni jalanan landai, kutemukan sebuah taman kecil seukuran halaman rumah yang kelihatannya cukup nyaman. Di seberang taman itu, di sisi yang berlawanan dengan jalan raya, ada tanggul batu alami yang agak condong. Sebenarnya tempat itu tidak seperti taman sama sekali –tak ada kolam air mancur atau pun tempat bermainnya. Hanya terdapat semacam anjang-anjang kecil tepat ditengah. Dindingnya dari anyaman kawat berpola belahketupat yang dipenuhi tanaman merambat. Ada semak-semak di sekelilingnya, dan ada tapak-tapak pijakan berbentuk persegi di tanah. Tak jelas untuk apa taman itu dibangun, namun seseorang sepertinya merawatnya secara teratur; pepohonan dan semak-semak itu terlihat dipangkas dengan rapi, dan tak ada rumput liar maupun sampah di sekitar. Sepertinya aku telah berjalan melewatinya tanpa menyadari keberadaannya sama sekali ketika naik.
Aku menuju taman itu dan duduk di bangku di sebelah anjang-anjang untuk menata pikiran. Kurasa mungkin sebaiknya aku menunggu sebentar di sekitar situ untuk melihat perkembangan keadaan (mungkin saja orang-orang akan mulai berdatangan). Setelah duduk baru kusadari betapa lelahnya diriku. Rasa lelah yang tak wajar, seakan-akan aku telah cukup lama kelelahan tanpa menyadarinya, dan baru sekarang aku merasakannya. Dari anjang-anjang itu terlihat pemandangan pelabuhan. Kapal-kapal kontainer besar berlabuh di dermaga. Dari atas pegunungan, kontainer-kontainer besi yang bertumpuk-tumpuk itu terlihat seperti kotak-kotak kaleng kecil yang biasanya kau taruh di atas meja sebagai wadah koin atau penjepit kertas.
Selang beberapa saat kemudian, kudengar suara laki-laki dari kejauhan. Suara itu seperti dipancarkan melalui pengeras suara. Tak dapat kutangkap apa yang diucapkannya, namun senantiasa ada jeda yang ajeg di antara setiap kalimat, dan suara itu begitu datar tanpa jejak emosi sama sekali, seakan-akan sedang mengumumkan sebuah berita penting yang harus disampaikan seobjektif mungkin. Terbersit pikiran bahwa itu mungkin adalah pesan pribadi yang ditujukan padaku, dan hanya padaku seorang. Seseorang sedang berusaha memberi tahu aku perihal sesuatu tak beres yang mungkin telah kulewatkan. Normalnya aku tidak akan dengan mudah berpikiran begitu, namun karena alasan tertentu yang tak kumengerti aku merasa bahwa mungkin saja memang begitulah adanya. Kudengarkan dengan saksama. Suara itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Pasti datangnya dari pengeras suara yang terpasang di atas atap sebuah mobil yang sedang berjalan pelan mendaki. Akhirnya aku pun menyadari apa itu: sebuah mobil yang berkeliling mengumumkan Pesan-pesan Kristiani.
“Setiap orang akan mati,” kata suara itu dengan nada tenang dan cenderung monoton. “Setiap manusia akan meninggalkan dunia ini pada waktunya. Tak seorang pun dapat menghindari kematian dan hari pembalasan setelahnya. Setelah kematian, setiap orang akan menerima pembalasan atas dosa-dosanya.”
Aku duduk di bangku, mendengarkan pesan itu. Betapa aneh mengetahui ada seseorang yang mau repot-repot menyampaikan pesan semacam itu di area pemukiman sepi di atas pegunungan seperti ini. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya kaya raya dan punya banyak mobil. Kuragukan bahwa mereka akan tertarik pada iming-iming pengampunan dosa. Ataukah sebenarnya iya? Status dan besaran penghasilan mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan dosa dan ampunan.
“Namun mereka yang mencari ampunan dalam Yesus Kristus dan benar-benar menyesali dosa-dosanya akan mendapatkan ampunan dari Tuhan. Mereka akan terhindar dari api Neraka. Percayalah pada Tuhan, karena hanya orang-orang yang percaya pada-Nya yang akan mendapatkan ampunan setelah kematian dan akan hidup dalam keabadian.”
Aku menunggu mobil penyebar Misi Kristiani itu muncul di jalanan di depanku dan mengatakan lebih banyak lagi tentang hari pembalasan setelah kematian. Kupikir waktu itu aku cuma sedang mengharapkan lebih banyak kata-kata dari suara yang terdengar penuh keyakinan semacam itu, tak peduli apa pun isi pesannya. Namun mobil itu tak pernah muncul. Dan, pada titik tertentu, suara itu kemudian mulai terdengar kian sayup-sayup, lalu tak berapa lama kemudian aku tidak lagi mendengarnya. Mobil itu pasti telah berbelok ke arah lain, menjauh dari tempatku berada. Setelah suara dari mobil itu benar-benar hilang, aku jadi merasa seperti seorang yang telah dicampakkan begitu saja oleh dunia.
*
Sebuah pemikiran tiba-tiba membentur kepalaku: mungkin semua ini sebenarnya adalah hoax yang sengaja dibuat oleh gadis itu. Ide –atau mungkin lebih tepat kusebut sebagai ilham—tersebut muncul begitu saja entah dari mana. Untuk alasan yang tak dapat kupahami, ia telah sengaja memberiku informasi palsu dan menyeretku hingga ke pegunungan terpencil ini pada suatu Minggu sore. Mungkin aku pernah melakukan sesuatu yang membuatnya memendam rasa dendam pribadi terhadapku. Atau mungkin, karena suatu alasan tertentu, ia jadi merasa benci padaku. Dan ia telah mengirimiku sebuah undangan untuk menghadiri pertunjukan piano yang sesungguhnya fiktif belaka dan saat ini mungkin sedang tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan (atau mungkin membayangkan) bagaimana ia telah berhasil melancarkan tipuannya dan betapa aku sekarang sedang kebingungan sendiri di sini.
Baiklah, tetapi adakah seseorang yang benar-benar seniat itu, yang sampai merencanakan suatu plot rumit hanya untuk mengerjai seseorang, begitu saja? Bahkan untuk sekadar mencetak undangan pasti membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Dapatkah seseorang bertindak sejauh dan setega itu? Tak dapat kuingat apa kiranya yang pernah kulakukan hingga membuatnya begitu membenciku. Namun terkadang kita menyakiti perasaan seseorang dan menyinggung harga dirinya tanpa kita sadari. Kucoba menerka-nerka kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin dapat melahirkan kebencian seperti ini, namun tak kutemukan satu pun yang cukup meyakinkan. Dan selagi coba kutelusuri lika-liku emosi ini tanpa menghasilkan apa-apa, pikiranku tiba-tiba macet. Dadaku tiba-tiba sesak.
Hal semacam ini kadang terjadi padaku sekali dua kali dalam setahun. Kupikir itu semacam hiperventilasi yang dipicu oleh stres. Jika aku terlalu memikirkan sesuatu sampai aku benar-benar kebingungan, tenggorokanku akan menyempit, dan paru-paruku tidak akan mendapatkan suplai udara yang cukup. Lalu aku akan panik, seakan-akan sedang tenggelam dan terseret arus, dan tubuhku jadi tidak dapat digerakkan. Satu-satunya yang dapat kulakukan adalah meringkuk, memejamkan mata, dan menunggu sampai tubuhku kembali normal dengan sendirinya. Simptom-simptom ini semakin jarang terjadi dan pada akhirnya tak pernah terjadi lagi seiring aku bertambah usia (dan pada titik tertentu, wajahku pun tak lagi gampang bersemu merah), namun waktu masih remaja permasalahan ini kadang kualami.
Di bangku dekat anjang-anjang itu, kupejamkan mataku rapat-rapat, kubungkukkan badan, dan aku menunggu sampai aku terbebas dari rasa sesak itu dengan sendirinya. Mungkin selama lima menit. Atau bahkan mungkin sampai lima belas menit. Aku pun tak tahu berapa lama. Selama itu yang bisa kulihat hanya pola-pola aneh muncul dan menghilang dalam kegelapan, dan kuhitungi mereka satu per satu, sambil terus berusaha menata kembali nafasku. Jantungku berdetak tak karuan di dalam rongga dadaku, seperti ada tikus-tikus yang sedang berlarian ke sana ke mari di dalamnya.
*
Karena terlalu fokus menghitung, perlu waktu cukup lama bagiku untuk menyadari kehadiran orang lain di situ. Rasanya ada seseorang yang sedang berdiri di depanku dan mengamatiku lekat-lekat. Perlahan-lahan kubuka mataku dan kudongakkan kepalaku sedikit. Jantungku masih berdegup keras seperti gendang yang ditabuh.
Tanpa kusadari seorang laki-laki tua telah duduk di bangku depanku dan memperhatikanku. Bukan hal mudah bagi seorang remaja menebak usia orang tua. Bagiku mereka semua terlihat seperti orang tua saja. Enam puluh, tujuh puluh –apa bedanya? Mereka tak lagi muda, itu saja. Laki-laki ini mengenakan kardigan wol biru kelabu, celana kurdori cokelat, dan sneakers biru tua. Semuanya kelihatan sudah tak lagi baru, meskipun tidak juga terlihat usang. Rambutnya yang abu-abu terlihat kaku dan tebal, dan di atas telinganya ada rambut-rambut mencuat sepert sayap burung ketika sedang mandi. Ia tidak berkaca mata. Tak dapat kuterka berapa lama sudah ia di situ, namun firasatku mengatakan bahwa ia telah mengamatiku cukup lama.
Sepintas kupikir ia akan bertanya, “apa kau baik-baik saja?,” atau semacam itu sebab aku pasti terlihat sedang bermasalah (dan memang sedang bermasalah). Itulah hal pertama yang terlintas di pikiranku ketika melihat orang tua itu. Tetapi ia tidak berkata apa-apa, tidak bertanya apa-apa, cuma menggenggam erat sebuah payung hitam yang terlipat seperti memegang sebuah tongkat. Payung itu memiliki gagang kayu berwarna cokelat kekuningan dan kelihatan cukup kokoh untuk digunakan sebagai senjata bilamana diperlukan. Kutebak ia pasti tinggal di sekitar sini, sebab tak kulihat ada barang lain yang dibawanya.
Aku duduk di situ berusaha mengendalikan nafasku, sementara orang tua itu mengamatiku dalam diam. Dia tidak berkedip sama sekali. Itu membuatku tak nyaman –seakan-akan aku baru saja memasuki halaman rumah seseorang tanpa ijin—dan aku ingin dapat segera bangkit dari bangku itu dan langsung menuju tempat perhentian bus. Namun entah mengapa, aku tak mampu berdiri. Waktu berlalu, dan tiba-tiba orang tua itu bicara.
“Sebuah lingkaran dengan banyak titik pusat.”
Aku tengadah menatapnya. Pandangan kami bertemu. Dahinya lebar sekali, hidungnya mancung. Mirip paruh burung. Aku tak mampu mengatakan apapun, maka orang tua itu cuma mengulang-ulang perkataannya dengan suara lirih: “Sebuah lingkaran dengan banyak titik pusat.”
Aku sama sekali tak mengerti apa yang hendak disampaikannya. Sebuah pemikiran muncul—jangan-jangan laki-laki ini adalah pengemudi mobil yang mengumumkan Pesan Kristiani melalui pengeras suara tadi. Mungkinkah ia telah memarkir mobilnya tak jauh dari sini dan sedang beristirahat? Tidak mungkin. Suaranya berbeda dari yang tadi kudengar. Suara yang di pengeras suara tadi terdengar jauh lebih muda. Atau mungkin tadi itu adalah suara rekaman.
“Lingkaran, maksudmu?” Aku memberanikan diri bertanya. Ia lebih tua dariku, dan sopan santun mengharuskan aku menanggapinya.
“Ada beberapa titik pusat—tidak, kadang kala jumlahnya tak terhingga—dan lingkaran itu tidak memiliki keliling.” Orang tua itu mengatakan ini sambil mengernyit, keriput di dahinya terlihat semakin jelas. “Dapatkah kau membayangkan lingkaran itu di benakmu?”
Pikiranku masih belum pulih sepenuhnya, namun kucoba memikirkannya. Sebuah lingkaran yang memiliki beberapa titik pusat dan tanpa keliling. Namun, sekeras apapun aku berusaha, tak dapat kubayangkan sama sekali.
“Aku tak bisa,” kataku.
Orang tua itu memandangku dalam diam. Seolah-olah dia mengharapkan jawaban yang lebih memuaskan dariku.
“Kurasa lingkaran semacam itu tidak pernah diajarkan dalam pelajaran matematika,” kutambahkan sekenanya.
Orang tua itu mengusap kepalanya pelan. “Tentu saja tidak. Itu jelas. Sebab hal seperti itu tidak diajarkan di sekolah. Kau pasti tahu itu.”
Aku pasti tahu? Mengapa orang tua ini beranggapan demikian?
“Apa lingkaran semacam itu benar-benar ada?” aku bertanya.
“Tentu saja,” kata orang tua itu, dengan beberapa kali anggukan. “Lingkaran itu ada. Namun tak semua orang dapat melihatnya.”
“Kau bisa melihatnya?”
Orang tua itu tidak menjawab. Pertanyaanku pun cuma menggantung begitu saja di udara selama beberapa saat, sebelum akhirnya memudar dan hilang.
Orang tua itu bicara lagi. “Dengar, kau mesti membayangkannya dengan kekuatanmu sendiri. Gunakan seluruh kebijaksanaan yang kau miliki untuk menggambarkannya. Sebuah lingkaran yang memiliki banyak titik pusat namun tanpa keliling. Kalau kau berusaha dengan sungguh-sungguh hinga kau seakan-akan sampai meneteskan keringat darah—barulah perlahan-lahan lingkaran itu akan mulai terlihat jelas.”
“Kedengarannya sulit,” kataku.
“Tentu saja,” kata orang tua itu, dengan nada seperti sedang melontarkan sesuatu yang keras dari mulutnya. “Tak ada sesuatu yang benar-benar layak didapatkan dengan mudah di dunia ini.” Kemudian, seperti hendak memulai paragraf baru, ia lalu berdeham membersihkan kerongkongannya. “Tapi, kalau kau mau meluangkan waktu dan berusaha, kalau kau bisa mendapatkan yang sulit itu maka ia akan menjadi krim hidupmu.”
“Krim?”
“Ada sebuah ungkapan dalam Bahasa Perancis: crème de la crème. Kau mengerti? Selain dari itu cuma hal-hal yang membosankan dan tak berharga sama sekali.”
Aku tidak benar-benar memahami apa yang dimaksud orang tua itu. Crème de la crème?
“Pikirkanlah,” kata orang tua itu. “Pejamkan matamu lagi, dan pikirkan semua itu. Sebuah lingkaran yang memiliki banyak titik pusat namun tanpa keliling. Otakmu diciptakan untuk memikirkan hal-hal yang sulit. Untuk membantumu mencapai titik di mana kau bisa memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kau pahami. Jangan malas dan bersikap masabodoh. Sekarang adalah masa yang kritis. Sebab ini adalah masa ketika otak dan hatimu sedang terbentuk dan mulai memadat.”
Kupejamkan mataku kembali dan kucoba membayangkan lingkaran itu. Aku tak ingin bermalas-malasan dan bersikap masabodoh. Namun, tak peduli seserius apapun aku memikirkan apa yang yang dikatakan orang tua itu, mustahil bagiku ketika itu untuk memahami maksudnya. Lingkaran yang kutahu adalah yang memiliki satu titik pusat dan sebuah garis lengkung yang menghubungkan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat tersebut. Bukankah lingkaran sebagamana yang dibicarakan oleh orang tua itu bertolak belakang dengan apa yang dikenal sebagai lingkaran pada umumnya?
Kupikir orang tua itu bukanlah seorang yang tak waras. Dan tidak pula kupikir bahwa ia mengerjaiku. Ia sedang berusaha menyampaikan sesuatu hal penting. Maka kucoba lagi untuk memahami, namun pikiranku cuma berputar-putar tanpa menghasilkan apa-apa. Bagamana mungkin ada sebuah lingkaran memiliki banyak (atau bahkan tak terhingga) titik pusat? Apakah ini semacam metafora filosofis tingkat tinggi? Aku menyerah dan kubuka mataku. Aku memerlukan lebih banyak petunjuk.
Namun orang tua itu tak lagi berada di situ. Kulihat sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang pun di taman itu. Seakan-akan ia memang tak pernah ada. Apakah semua itu cuma imajiasiku saja? Tidak, jelas semua itu bukan fantasi belaka. Ia tadi ada di situ di depanku, menggenggam erat payungnya, berbicara lirih, menyampaikan pertanyaan aneh, dan kemudian pergi.
Kusadari nafasku sudah kembali normal, pelan dan teratur. Arus yang menghanyutkanku telah menghilang. Di sana sini mulai terlihat celah di antara awan tebal di atas pelabuhan. Berkas-berkas cahaya menerobos, menimpa sebuah bilik alumunium di puncak crane, seolah-olah cahaya itu memang sengaja diarahkan supaya jatuh tepat di titik itu saja. Kupandangi cukup lama, dan aku terhanyut oleh pemandangan yang hampir-hampir seperti dongeng itu.
Buket kecil bunga-bunga merah, terbalut dalam lembaran plastik transparan, di sisiku. Seperti semacam bukti akan peristwa-peristiwa aneh yang terjadi padaku. Aku menimbang-nimbang apa yang sebaiknya kulakukan terhadapnya, dan akhirnya kuputuskan untuk meninggalkannya begitu saja di bangku dekat anjang-anjang. Bagiku sepertinya itulah pilihan yang terbaik. Aku berdiri dan berjalan menuju perhentian bus yang semula kutuju. Angin mulai berhembus mencerai-beraikan awan di atas sana.
*
Setelah selesai kuceritakan kisah ini, ada jeda hening selama beberapa saat, kemudian kawan mudaku berkata, “Aku tidak terlalu memahaminya. Apa yang sebenarnya telah terjadi waktu itu? Apakah ada pesan tersirat atau benang merah di baliknya?”
Kejadian yang pernah kualami di atas pegunungan Kobe pada suatu Minggu sore di musim gugur itu—menelusuri peta pada selembar undangan menuju tempat di mana sebuah pertunjukan piano seharusnya berlangsung, hanya untuk menemukan sebuah gedung yang tak lagi terurus—apakah artinya semua itu? Dan mengapa semua itu terjadi? Itulah yang coba ditanyakan oleh kawanku. Sebuah pertanyaan yang wajar adanya, mengingat cerita yang kusampaikan padanya memang tidak membawa kesimpulan apa-apa.
“Aku sendiri, hingga saat ini, tidak pernah mengerti,” aku mengaku.
Seperti sebuah teka-teki kuno, selamanya tak terpecahkan. Yang terjadi hari itu benar-benar sulit dipahami, sulit dijelaskan, dan menyisakan hanya kebingungan dan kegundahan dalam diriku yang baru berusia delapan belas tahun. Demikian membingungkannya sampai, untuk sesaat, aku hampir-hampir tersesat kehilangan arah.
“Namun kurasa,” kataku, “perihal pesan tersirat atau benang merah di balik peristiwa itu bukanlah sesuatu yang penting.”
Kawanku terlihat bingung. “Maksudmu tidak ada perlunya mengetahui arti di balik itu semua?”
Aku mengangguk.
“Tapi kalau itu terjadi padaku,” katanya, “Aku tidak akan pernah tenang. Aku harus mengetahui kebenaran tentang mengapa hal seperti itu terjadi. Kalau aku jadi kamu, begitulah.”
“Yap, tentu saja. Dulu aku juga tak bisa tenang. Semua itu sangat mengganggu pikiranku. Juga menyakitkan di saat yang sama. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, setelah semua itu jauh berlalu, rasanya tidak begitu penting lagi, tidak layak dijadikan beban pikiran. Rasanya semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan krim kehidupan.”
“Krim kehidupan,” ulangnya.
“Hal-hal macam ini kadang terjadi,” kukatakan padanya. “Peristiwa-peristiwa tak masuk akal, tak lumrah, namun sangat mengganggu. Kupikir kita tak perlu terlalu memikirkannya, cukup pejamkan mata dan biarkan saja ia berlalu. Seperti menyelam di bawah gulungan ombak besar.”
Kawan mudaku itu terdiam selama beberapa saat, memikirkan ombak besar. Ia adalah seorang peselancar berpengalaman, dan ada banyak hal serius yang dapat dia pikirkan tentang ombak. Akhirnya ia pun bicara. “Tapi tidak memikirkan apa-apa juga bisa jadi sangat sulit dilakukan.”
“Kau benar. Itu bisa sangat sulit.”
Tidak ada sesuatu hal pun yang layak didapatkan dengan mudah di dunia ini, orang tua itu pernah bilang begitu, dengan sangat tak terbantahkan, seperti Pythagoras menerangkan teoremanya.
“Mengenai lingkaran dengan banyak titik pusat namun tanpa keliling itu,” kawanku bertanya. “Kau sudah menemukan jawabannya?”
“Pertayaan yang bagus,” kataku. Kuusap perlahan kepalaku. Sudahkah?
Dalam kehidupanku, setiap kali peristwa janggal yang tak masuk akal terjadi (bukan berarti hal semacam ini sering terjadi, namun beberapa kali memang pernah terjadi), aku selalu kembali pada lingkaran itu—lingkaran dengan banyak titik pusat namun tanpa keliling. Dan, sebagaimana yang kulakukan waktu berusia delapan belas tahun di bangku dekat anjang-anjang itu, kupejamkan mataku dan kucoba mendengarkan detak jantungku sendiri.
Kadang aku merasa dapat memahami seperti apa lingkaran itu, namun semakin coba kupahami semakin aku jadi tak paham. Lingkaran ini, mungkin saja, bukanlah lingkaran yang memiliki bentuk aktual yang nyata melainkan hanya dapat ada di dalam pikiran kita saja. Ketika kita benar-benar mencinta seseorang, atau merasakan kasih yang mendalam, atau memiliki gagasan ideal mengenai bagaimana dunia ini seharusnya, atau ketika kita menemukan keyakinan kita (atau sesuatu yang serupa dengan keyakinan)—ketika itulah kita akan memahami dan menerima keberadaan lingkaran itu di dalam hati kita. Namun tentu saja ini tak lebih dari sekedar pendapat pribadiku saja, sekedar usahaku untuk mencoba memahami lingkaran itu.
Otakmu diciptakan untuk memikirkan hal-hal yang sulit. Untuk membantumu mencapai titik di mana kau memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kau pahami. Dan itulah krim kehidupanmu. Segalanya selain itu adalah hal-hal yang membosankan dan tidak berarti. Itulah yang pernah dikatakan laki-laki tua berambut kelabu itu kepadaku. Di suatu Minggu sore yang mendung di akhir musim gugur, di atas pegunungan di Kobe, ketika kuggenggam sebuket kecil bunga-bunga merah di tanganku. Pun sampai sekarang, setiap kali ada sesuatu yang mengganggu benakku, akan kubenamkan pikiranku kembali ke dalam lingkaran spesial itu, dan hal-hal yang membosankan dan tak berarti. Dan krim unik yang aku yakin pasti ada di sana, jauh di dalam diriku.[]
__________
Bintan, 25-31 Agustus 2019
diterjemahkan sekenanya dari cerpen berjudul Cream karya Haruki Murakami (Naskah asli: https://www.newyorker.com/magazine/2019/01/28/cream)
-Mu
Antara ilalang dan rembulan
Pikiranku jauh melayang
Menembus gugusan bintang-bintang
Perasaanku dalam terbenam
Di dasar batu-batu karang
Ditelan gelombang lautan pasang
Dan aku menghilang
Dalam kelebat bayang-bayang
-Mu
Bintan, 16 Juni 2019 malam
Malam Di Sini
Di sini rembulan benderang melebihi terang lampu-lampu jalanan di kota-kota yang penuh persimpangan.
Nyanyian jangkrik melebur dingin dinding-dinding sunyi yang mengepung jiwa-jiwa sepi dalam fana pikirannya.
Membebaskan ribuan kunang-kunang terbang mengembara di belantara bayang-bayang dunia yang jatuh di langit tanpa cakrawala.
Mengubur kata di bawah bangkai huruf-huruf tak dikenal. Menenggelamkannya ke dalam lautan suara tak terdengar.
Di sini malam begitu pekat melarutkan perasaan dan impian dalam pusaran waktu yang terpaut di jejak rembulan.
Angin sedang berkelana entah ke mana, meninggalkan nyiur tanpa lambaian dan laut tanpa gelombang.
Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara petir menggelegar. Di sini badai bisa datang dan pergi kapan saja.
Begitu saja.
Bintan, 17 Mei 2019 (malam)
Nyanyian jangkrik melebur dingin dinding-dinding sunyi yang mengepung jiwa-jiwa sepi dalam fana pikirannya.
Membebaskan ribuan kunang-kunang terbang mengembara di belantara bayang-bayang dunia yang jatuh di langit tanpa cakrawala.
Mengubur kata di bawah bangkai huruf-huruf tak dikenal. Menenggelamkannya ke dalam lautan suara tak terdengar.
Di sini malam begitu pekat melarutkan perasaan dan impian dalam pusaran waktu yang terpaut di jejak rembulan.
Angin sedang berkelana entah ke mana, meninggalkan nyiur tanpa lambaian dan laut tanpa gelombang.
Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara petir menggelegar. Di sini badai bisa datang dan pergi kapan saja.
Begitu saja.
Bintan, 17 Mei 2019 (malam)
Lilin
Dia adalah nyala lilin yang tabah
menerangi rembulan.
Ditemaninya gelap malam yang diam-diam selalu mencuri-curi pandang kepada rembulan dari bawah dahan pohon-pohon cemara yang berbisik ke telinga-telinga sepi perihal kabar yang terbawa angin dari negeri-negeri jauh.
Negeri-negeri yang hanya dapat dikunjungi melalui mimpi-mimpi yang mengambang di antara lelah dan lelapmu.
Yang selalu kan kau ingat meski tak pernah dapat kau ceritakan.
Yang selalu dapat membuatmu tiba-tiba tersenyum tanpa alasan.
Yang selalu dapat membuatmu tersadar betapa jantungmu senantiasa berdetak di luar kehendakmu.
Jogja, Februari - 3 April 2019
Sebuah Lanskap Tentang Kota
Ini adalah cuplikan kecil dari lukisan berjudul Blooming Flower karya Yoyo Siswoyo yang dipajang di galeri Kiniko Art dalam rangka Solo Exhibition-nya yang bertajuk "Dari Timur ke Barat". Di antara semua lukisan yang dipajang di galeri itu, saya merasa paling suka melihat yang ini. Bukan berarti lukisan ini memang yang paling bagus di antara yang lainnya. Mungkin, kebetulan saja saya merasa lebih dapat mencerna lukisan yang satu ini dibanding lukisan lainnya. Walaupun, kalau ditelisik dari judul lukisannya sendiri, apa yang saya lihat pada lukisan ini ternyata tidak begitu sesuai juga dengan judul tersebut.
Kalau menyaksikan lukisan ini secara utuh sebagai satu kesatuan (tanpa terlebih dahulu mengetahui judulnya), saya seperti menyaksikan lanskap sebuah kota dari suatu ketinggian. Mungkin lebih tepat dikatakan sebagai bayang-bayang sebuah kota dengan latar belakang langit putih.
Saya melihat ada tiang-tiang antena yang menjulur di atas puncak-puncak gedung. Saya melihat ada jendela-jendela yang meloloskan sedikit cahaya dari dalam gedung melalui celah-celah bingkainya. Saya melihat hingar-bingar dalam gelapnya. Seperti pesta kembang api dan mercon. Dan riuh percakapan di antara berbagai macam (warna-warni) manusia. Dan begitu banyak rahasia, banyak misteri, di balik tembok-tembok remangnya yang menciptakan labirin ruang dan waktu, di mana kedua hal tersebut kemudian saling melarutkan satu sama lain.
Saya melihat kabut dan asap. Saya melihat mendung dan hujan. Dan (belakangan saya kemudian baru menyadarinya) betapa kota sepertinya memang penuh dengan kekontrasan. Mungkin itulah yang membuat saya mencerna lukisan tersebut sebagai sebuah lanskap tentang kota. Putih dan hitam, dan warna-warna menyala di tengah kegelapan.
Baru setelah membaca judulnya, lalu melihat kembali lukisan itu dari jarak yang lebih jauh lagi, saya bisa melihat bunga-bunga bermekaran itu. Tetapi bagi saya, lukisan itu tetap adalah sebuah lanskap tentang kota.
27 Februari 2019
Pertemuan Pertama
Kalau coba mengingat-ingat lagi berbagai hal yang sudah terjadi, aku selalu mendapati betapa semua ini adalah sebuah kenyataan yang aneh. Sebab aku tak bisa ingat kapan pertama kali aku menemukan kehadiranmu dalam hidupku. Aku tak ingat kapan kita pernah berkenalan secara wajar sebagaimana layaknya sebuah perkenalan antar dua manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Samar-samar aku seperti ingat bahwa kita pernah sekelas, entah di mata kuliah apa. Bahwa kadang-kadang kita berpapasan di perjalanan antara gedung kuliah dengan fakultas, atau di koridor remang-remang di antara kelas-kelas perkuliahan. Atau kadang-kadang aku melihatmu sedang berjalan di kejauhan. Tapi semua itu begitu samar-samar adanya sehingga aku tidak bisa tidak curiga bahwa itu cuma khayalanku saja.
Tetapi, bukankah harus ada sebuah titik permulaan bagi setiap garis? Tidak terkecuali garis yang ditorehkan takdir tentang kita. Mungkin aku sekedar luput merekamnya dalam ingatanku saja.
Tapi tak pelak, itu membuat semua ini jadi terasa aneh. Seolah-olah aku sudah mengenalmu jauh-jauh hari sebelum benar-benar bertemu denganmu. Mungkin aku terlalu banyak menghayalkan sebuah perkenalan denganmu sebelum kita benar-benar sempat bertemu di dunia nyata. Mungkin aku pertama kali mengenalmu di dunia yang sama sekali lain dari dunia ini.
Mungkin perkenalan itu terjadi di dunia ide, mimpi, atau angan-angan. Mungkin karena aku pernah membaca tulisan-tulisanmu sebelum bertemu denganmu secara langsung. Dan mungkin kepingan-kepingan buah pikiran dan perasaanmu itu terasa demikian tak asing bagiku ketika itu, sehingga dengan mudahnya tercampur baur ke dalam dunia angan-anganku.
Dan oleh karena, di dalam dunia angan-anganku, waktu bukanlah sebuah konsep yang terlalu penting sebagaimana adanya di dunia nyata ini (waktu berlaku dalam cara yang jauh berbeda di dalam angan-anganku), jadilah aku tak mampu menemukan letak koordinat peristiwa pertemuan pertama kita itu di dalam kerangka ruang-waktu objektif sebagaimana yang berlaku di dunia ini. Mungkin begitulah adanya sehingga semua ini terasa demikian aneh dan tak wajar.
Tetapi selalu ada kemungkinan akan datangnya pertanyaan dari orang-orang tentang pertemuan pertama kita, kan? Dan karena waktu merupakan suatu konsep acuan yang begitu penting buat mereka, tentu kita akan ditagih untuk memberi jawaban yang punya sangkan-paran jelas di rentang garis waktu yang berlaku di dunia nyata ini.
Demikianlah, sehingga aku ingin mengusulkan dua peristiwa yang sekiranya layak dianggap sebagai pertemuan kita yang pertama kali.
Peristiwa yang pertama, adalah pada malam bulan Februari itu, ketika kita, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah jagad raya, saling berjabat tangan sebelum berlaga di arena permainan. Usul ini, tentu dengan pertimbangan bahwa jabat tangan adalah sebuah tanda pertemuan yang cukup formal dan dapat diterima oleh khalayak. Meskipun kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya terjadi jauh setelah kita seperti sudah cukup saling kenal satu sama lain, sih.
Maka dari itu, aku mengusulkan peristiwa kedua. Pada suatu malam di akhir September tiga tahun (lebih dikit) yang lalu, di bawah terang bulan purnama (?), kita berjumpa di permukaan rembulan. Waktu itu kita mungkin memang tidak sedang berada di satu tempat yang sama. Aku sedang berusaha menikmati kopi dingin di sebuah warung kopi 24 jam sementara rembulan berpendar di langit gelap dan kebetulan dapat kulihat pada permukaan kopi dalam cangkirku sebelum kemudian kutengok melalui sela-sela tirai bambu yang diturunkan untuk menahan dinginnya angin. Sedangkan kamu, entah berada di mana dan sedang apa, namun kubayangkan sebuah kemungkinan (yang aku suka) bahwa kamu juga sedang melihat rembulan yang sama. Begitulah, aku melihatmu pada rembulan, dan (kubayangkan) engkau pun melihatku di rembulan yang sama. Lalu kita saling menyapa lewat bait-bait puisi.
Betapa itu tentunya akan terdengar sangat tidak masuk akal di telinga orang-orang. Tetapi bukankah kehidupan memang seringkali terasa tidak masuk akal? Toh, kehidupan ini berlangsung bukan menuruti seberapa sempit (atau luas) ruang di kepalamu untuk menampungnya. Ia sudah terlebih dahulu berlangsung begitu saja, sebelum kita sempat memahaminya. Dan apa yang kita sebut sebagai akal, baru berkembang belakangan, supaya kita mampu membuka pemahaman terhadap luasnya hamparan kemungkinan yang dikandung kehidupan.
Apapun itu maksudnya. Aku juga tak mengerti. Kadang aku memang suka ngelantur kalau lagi nulis.
Bagaimana menurutmu?
~
Jogja, 21 Februari 2019
Samar-samar aku seperti ingat bahwa kita pernah sekelas, entah di mata kuliah apa. Bahwa kadang-kadang kita berpapasan di perjalanan antara gedung kuliah dengan fakultas, atau di koridor remang-remang di antara kelas-kelas perkuliahan. Atau kadang-kadang aku melihatmu sedang berjalan di kejauhan. Tapi semua itu begitu samar-samar adanya sehingga aku tidak bisa tidak curiga bahwa itu cuma khayalanku saja.
Tetapi, bukankah harus ada sebuah titik permulaan bagi setiap garis? Tidak terkecuali garis yang ditorehkan takdir tentang kita. Mungkin aku sekedar luput merekamnya dalam ingatanku saja.
Tapi tak pelak, itu membuat semua ini jadi terasa aneh. Seolah-olah aku sudah mengenalmu jauh-jauh hari sebelum benar-benar bertemu denganmu. Mungkin aku terlalu banyak menghayalkan sebuah perkenalan denganmu sebelum kita benar-benar sempat bertemu di dunia nyata. Mungkin aku pertama kali mengenalmu di dunia yang sama sekali lain dari dunia ini.
Mungkin perkenalan itu terjadi di dunia ide, mimpi, atau angan-angan. Mungkin karena aku pernah membaca tulisan-tulisanmu sebelum bertemu denganmu secara langsung. Dan mungkin kepingan-kepingan buah pikiran dan perasaanmu itu terasa demikian tak asing bagiku ketika itu, sehingga dengan mudahnya tercampur baur ke dalam dunia angan-anganku.
Dan oleh karena, di dalam dunia angan-anganku, waktu bukanlah sebuah konsep yang terlalu penting sebagaimana adanya di dunia nyata ini (waktu berlaku dalam cara yang jauh berbeda di dalam angan-anganku), jadilah aku tak mampu menemukan letak koordinat peristiwa pertemuan pertama kita itu di dalam kerangka ruang-waktu objektif sebagaimana yang berlaku di dunia ini. Mungkin begitulah adanya sehingga semua ini terasa demikian aneh dan tak wajar.
Tetapi selalu ada kemungkinan akan datangnya pertanyaan dari orang-orang tentang pertemuan pertama kita, kan? Dan karena waktu merupakan suatu konsep acuan yang begitu penting buat mereka, tentu kita akan ditagih untuk memberi jawaban yang punya sangkan-paran jelas di rentang garis waktu yang berlaku di dunia nyata ini.
Demikianlah, sehingga aku ingin mengusulkan dua peristiwa yang sekiranya layak dianggap sebagai pertemuan kita yang pertama kali.
Peristiwa yang pertama, adalah pada malam bulan Februari itu, ketika kita, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah jagad raya, saling berjabat tangan sebelum berlaga di arena permainan. Usul ini, tentu dengan pertimbangan bahwa jabat tangan adalah sebuah tanda pertemuan yang cukup formal dan dapat diterima oleh khalayak. Meskipun kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya terjadi jauh setelah kita seperti sudah cukup saling kenal satu sama lain, sih.
Maka dari itu, aku mengusulkan peristiwa kedua. Pada suatu malam di akhir September tiga tahun (lebih dikit) yang lalu, di bawah terang bulan purnama (?), kita berjumpa di permukaan rembulan. Waktu itu kita mungkin memang tidak sedang berada di satu tempat yang sama. Aku sedang berusaha menikmati kopi dingin di sebuah warung kopi 24 jam sementara rembulan berpendar di langit gelap dan kebetulan dapat kulihat pada permukaan kopi dalam cangkirku sebelum kemudian kutengok melalui sela-sela tirai bambu yang diturunkan untuk menahan dinginnya angin. Sedangkan kamu, entah berada di mana dan sedang apa, namun kubayangkan sebuah kemungkinan (yang aku suka) bahwa kamu juga sedang melihat rembulan yang sama. Begitulah, aku melihatmu pada rembulan, dan (kubayangkan) engkau pun melihatku di rembulan yang sama. Lalu kita saling menyapa lewat bait-bait puisi.
Betapa itu tentunya akan terdengar sangat tidak masuk akal di telinga orang-orang. Tetapi bukankah kehidupan memang seringkali terasa tidak masuk akal? Toh, kehidupan ini berlangsung bukan menuruti seberapa sempit (atau luas) ruang di kepalamu untuk menampungnya. Ia sudah terlebih dahulu berlangsung begitu saja, sebelum kita sempat memahaminya. Dan apa yang kita sebut sebagai akal, baru berkembang belakangan, supaya kita mampu membuka pemahaman terhadap luasnya hamparan kemungkinan yang dikandung kehidupan.
Apapun itu maksudnya. Aku juga tak mengerti. Kadang aku memang suka ngelantur kalau lagi nulis.
Bagaimana menurutmu?
~
Jogja, 21 Februari 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)